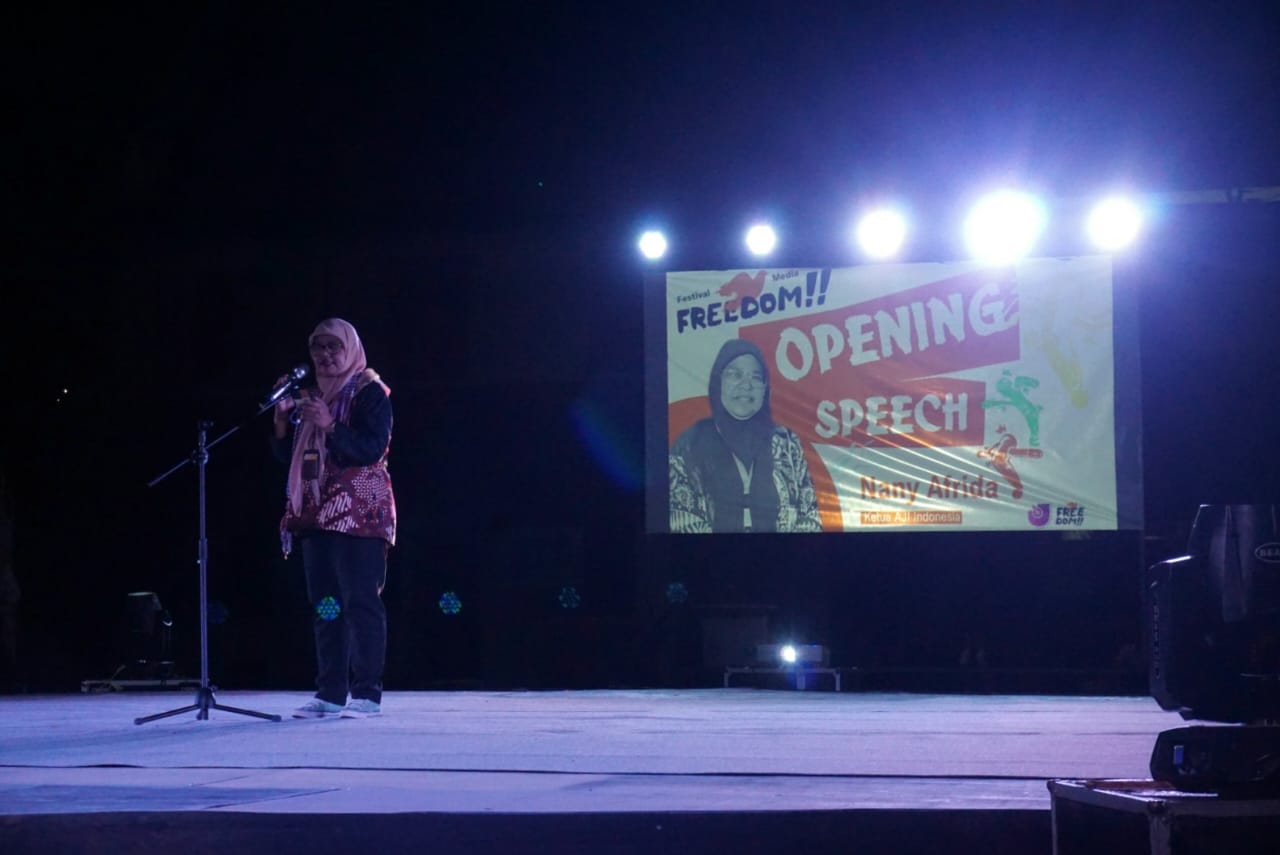Oleh Anza Suseno
INDEPENDEN-- Di sebuah sudut Kampung Babakan, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdiri sebuah rumah reyot yang nyaris roboh berukuran 4x3 meter persegi.
Pak Odang tinggal di sana bersama istri dan anak-anaknya. Lelaki berusia 53 tahun itu membawa keluarga berteduh di rumah yang berdinding kayu lapuk, atap bocor, serta tiang yang doyong.
Rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya.
"Sebenarnya kalau lihat rumah ini, saya sedih banget, Pak," ucap Pak Odang dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalau naik ke atas itu, semua udah pada patah. Kalau ada angin besar, mungkin sudah ambruk. Apalagi kalau hujan, dapur saya kebanjiran."
Bertahan hidup bagi Pak Odang bukan perkara mudah. Sudah 14 tahun ia bekerja bantu-bantu di sebuah penginapan dengan gaji hanya satu juta rupiah per bulan. Sementara istrinya berjuang dengan bekerja sebagai tukang cuci dan gosok, hanya menghasilkan 400 ribu rupiah sebulan. Dengan lima anak yang harus diberi makan dan disekolahkan, angka itu jauh dari cukup.
"Kadang anak saya dalam satu minggu cuma bisa sekolah dua atau tiga hari. Bukan karena malas, tapi nggak ada bekalnya," ujarnya lirih. "Yang SMP butuh 10 ribu per hari, yang SD 5 ribu. Itu baru buat mereka, belum buat saya dan istri. Saya perlu makan. Gaji satu juta nggak cukup, Pak. Kadang saya harus kasbon dua kali seminggu."

Sebagai warga yang tinggal di kawasan ring 1 proyek panas bumi, seharusnya Pak Odang dan warga sekitar merasakan cipratan keuntungan ekonomi. Namun, kenyataannya berbeda.
"Nggak ada perubahan. Masyarakat sini cuma jadi penonton. Paling kita lihat mobil-mobil proyek lewat. Yang kerja orang luar. Bantuan juga minim. Terakhir saya dapat BLT, cuma 400 ribu. Itu pun udah habis buat makan," kata lelaki itu.
Selain tekanan ekonomi, lingkungan sekitar pun tak lagi ramah. Satwa liar turun ke permukiman, mencari makanan di antara rumah-rumah warga.
"Monyet di sini banyak banget. Bisa sampai 50 ekor lebih. Mereka ngacak-ngacak genteng, ambil pisang, singkong, jambu. Saya menanam singkong buat makan, tapi pas mau diambil udah habis semua dimakan monyet. Kadang saya ketapel mereka, tapi nggak tega juga," keluh Pak Odang lagi.
Di balik segala keterbatasan, harapan Pak Odang sesederhana rumahnya.
"Saya nggak minta banyak. Cuma ingin rumah yang layak, yang nggak bocor kalau hujan. Anak-anak bisa tidur nyaman. Sekarang ini bukan rumah, kata orang, tapi kandang ayam. Tapi di sinilah saya berteduh. Di sinilah saya hidup," ujar lelaki itu.
Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk termenung, memandangi ubin semen yang dingin, lantai yang telah menjadi saksi dari perjuangannya yang tak berkesudahan.
Hanya berjarak delapan kilometer dari Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Geothermal yang berdiri megah di Gunung Salak, kehidupan Odang dan banyak warga lainnya justru tetap dalam bayang-bayang kesulitan.
“Kadang-kadang saya suka sedih, nangis dalam hati saya. Kenapa mau makan saja harus mencari belas kasih dulu,” ujar Odang lirih.
Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sering kali, Odang dan keluarganya harus menahan lapar puasa yang bukan karena Ramadan, bukan pula karena ibadah sunnah, tetapi karena keadaan yang memaksa.

Odang pernah berharap anaknya bisa bekerja di proyek itu. Namun, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa untuk melamar kerja saja butuh uang pendaftaran. “Mesti ada uang dulu buat masuk Ormas. Kenapa mau kerja harus bayar? Kalau saya punya uang, mending buat beli beras aja,” katanya.
Benar saja, dana-dana yang seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat daerah penghasil, nyatanya hanya mengalir ke tempat-tempat yang tak pernah menyentuh kehidupan mereka.
Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin nyata, sementara perusahaan dan pemerintah sibuk bertukar argumen tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab di tengah semua itu, masyarakat sekitar hanya bisa menjadi penonton menyaksikan sebuah pertandingan yang tak pernah mereka undang, tetapi dampaknya mereka rasakan begitu dalam.
Sementara perusahaan terus mengembangkan proyeknya, dampaknya terhadap lingkungan semakin terasa. Di tengah deru mesin proyek yang terus berjalan, suara masyarakat seperti Odang tenggelam. Harapan akan kehidupan yang lebih baik semakin redup. Mereka yang berada di garis depan eksploitasi sumber daya justru tetap berada di garis belakang kesejahteraan.
Kemiskinan di Bayang-Bayang Eksploitasi Panas Bumi
Benar saja berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Kabandungan tercatat sebanyak 46.643 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.390 jiwa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berarti mereka termasuk dalam kategori masyarakat prasejahtera.
Sementara itu, hanya 6.253 jiwa yang terdata sebagai masyarakat sejahtera. Situasi serupa terjadi di Kecamatan Kalapanunggal, yang memiliki total populasi 54.381 jiwa. Dari jumlah tersebut, 43.857 jiwa masuk dalam data DTKS, sedangkan hanya 10.524 jiwa yang terdata sebagai masyarakat sejahtera. Data ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk di sekitar wilayah operasi panas bumi masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Ironisnya, kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat eksploitasi panas bumi di Jawa Barat. Dengan sumber daya energi yang begitu besar, seharusnya ada dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan industri energi terbarukan tidak serta-merta membawa perubahan signifikan bagi penduduk setempat.

Ekspansi Proyek Panas Bumi
Diketahui sejak tahun 1981 Mega Proyek Strategis Negara ini berdiri di atas zona pemanfaatan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sebuah ekosistem yang sejatinya menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati di Jawa Barat.
Dengan luas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Salak mencapai 10.000 hektar, proyek ini telah mengalokasikan 228,69 hektare untuk eksploitasi energi, termasuk penggunaan 116,34 hektare bagi Unit 1-2 pada tahun 1994 dan 112,35 hektar bagi Unit 3-6 pada tahun 1997, yang terus berkembang hingga 224,70 hektare.
Meskipun diklaim sebagai sumber energi bersih, ekspansi ini memunculkan dilema serius sejauh mana eksploitasi ini benar-benar berkontribusi pada energi berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekologis? Penebangan hutan, gangguan terhadap habitat satwa liar, serta potensi konflik dengan masyarakat adat dan petani lokal menjadi bayangan gelap di balik narasi keberlanjutan yang diusung pemerintah.
Dilihat secara administrasi yang didapat dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT. Star Energy ini masuk dalam 2 terbesar di Dunia yang diapit oleh 3 Wilayah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak.
Di dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, Desa Kabandungan, merupakan desa yang menjadi sebagai alamat pintu masuk dan terdekat dengan proyek tersebut atau termasuk dalam ring 1.

Proses awal eksplorasi panas bumi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memerlukan pembukaan lahan yang ketat. Lahan-lahan yang digunakan terutama untuk pembangunan fasilitas produksi seperti tapak sumur (wellpad), jalur akses, perpipaan, dan kantor operasional. Area ini tersebar dalam pola menjari, bukan berupa lahan yang dibabat habis dalam satu kawasan.
Dari total izin penggunaan lahan seluas 228,69 hektare, sebagian besar tetap dikelilingi oleh vegetasi hutan yang utuh.
“Ketika eksplorasi dimulai, pembukaan lahan memang dilakukan, tetapi hanya di awal saja. Setelah masuk tahap pemanfaatan, kawasan yang terbuka mulai ditanami kembali sehingga rimbun lagi. Pohon-pohon yang ditebang pun ditimbun di lokasi sesuai regulasi, tidak boleh dibawa keluar,” ujar Koko Komarudin, Kepala Urusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, saat ditemui di Kantor Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Langkah ini memastikan bahwa aktivitas panas bumi tetap meminimalkan dampak pada ekosistem hutan. Bahkan, kawasan di sekitar jalur pipa dan fasilitas produksi tetap dipenuhi vegetasi, sehingga aspek konservasi tetap terjaga.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Star Energy adalah pembangunan Binary Power Plant.
Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan sisa panas dari uap sebelum masuk ke sumur injeksi. Sisa panas tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin tambahan yang mampu menghasilkan energi. Pembangunan ini selesai pada pertengahan tahun 2024 dan kini tengah diikuti oleh pembangunan WLPTU (Wellpad Power Generation Unit).
“Kami memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan sesuai dokumen rencana, seperti Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jangka Panjang Panas Bumi (RPP JLPB) yang diperbarui setiap lima tahun dan RKTPJLPB yang disusun tiap tahun. Semua aktivitas sudah terintegrasi dalam rencana ini,” jelasnya.
Pengawasan ketat dilakukan sejak tahap awal, termasuk pendampingan dalam penebangan pohon, pengelolaan limbah, dan pencegahan dampak lingkungan seperti sedimentasi yang dapat mengganggu aliran sungai.
Sungai Cisaketi, salah satu sungai besar di kawasan ini, menjadi perhatian utama. Anak-anak sungainya tetap dijaga agar tidak terganggu oleh aktivitas pembangunan.

Proses pembangunan tidak luput dari tantangan.
Pada tahap awal pembangunan Binary Power Plant, sempat terjadi keluhan dari masyarakat terkait kekeruhan air sungai akibat aktivitas kontraktor. Namun, langkah cepat diambil dengan membangun dan penyekat untuk mengendalikan lumpur dan sedimentasi agar tidak mencemari sungai besar.
“Meski sempat ada kekeruhan, hal ini langsung ditindaklanjuti. Kami bekerja sama dengan kontraktor dan melakukan inspeksi lapangan secara rutin untuk memastikan dampaknya bisa diminimalkan,” tambahnya.
Proyek panas bumi di kawasan konservasi seperti TNGHS dimungkinkan berkat regulasi yang telah diperbarui, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-undang ini mengubah status panas bumi dari kategori pertambangan menjadi bagian dari jasa lingkungan, sehingga memungkinkan pemanfaatannya di kawasan konservasi.
“Dengan regulasi ini, panas bumi dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan kelestarian kawasan konservasi. Kami juga mengikuti Peraturan Menteri LHK Nomor P.4 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan panas bumi di kawasan konservasi,” pungkasnya.
Selain itu, pemerintah juga sedang menggodok peraturan menteri tematik yang akan menyatukan pengelolaan jasa lingkungan, termasuk wisata, air, dan panas bumi, dalam satu regulasi terpadu
Sementara itu PLTP merupakan salah satu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga mendukung target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.
Teknologi yang digunakan dalam PLTP di Jawa Barat terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu Dry Steam, Flash Steam, dan Binary Geothermal Power Plant.
PLTP Gunung Salak sendiri menggunakan teknologi Flash Steam.

Selama lebih dari empat dekade, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Salak telah menjadi penyedia energi terbarukan di wilayah Pulau Jawa, Madura hingga Bali (JAMALI) Indonesia.
Dengan 115 sumur produksi yang menghasilkan daya sebesar 377 MW, PLTP ini berkontribusi besar dalam pasokan listrik nasional. Dengan kapasitas tersebut, PLTP Gunung Salak menjadi salah satu fasilitas geothermal terbesar di Indonesia.
Sejak eksplorasi dan eksploitasi dimulai pada tahun 1982 hingga 2024. Dalam periode tersebut, sebanyak 115 sumur produksi panas bumi telah dibangun, mencapai kapasitas 377 MW. Untuk meningkatkan daya hingga target 495 MW, perusahaan Star Energy berencana melakukan pengeboran tambahan sebanyak 15 sumur pada tahun 2025.

Namun, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia. Habitat fauna endemik seperti elang jawa, si penguasa langit sebagai indikator terakhir, juga ikut terdampak. Dalam kondisi demikian, elang jawa harus dapat beradaptasi dengan uap panas bumi yang semakin mendominasi wilayahnya.
Dana Samar Penghasil Panas Bumi

Di balik deru mesin dan pipa-pipa raksasa yang mengalirkan energi dari perut bumi, kehidupan masyarakat di sekitar daerah penghasil panas bumi tetap berjalan dalam ironi yang sunyi. Mereka yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek ini, justru masih merasakan getirnya keterbatasan ekonomi. Namun, satu fakta tak terbantahkan, dana-dana yang seharusnya menjadi berkah telah mengalir. Pertanyaannya, ke mana perginya?
Berkaca pada keadaan masyarakat sekitar daerah penghasil, ternyata perusahaan geothermal telah menggelontorkan dana kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dana-dana tersebut, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Bonus Produksi (BP), serta dana Corporate Social Responsibility (CSR), seharusnya mampu menjadi angin segar bagi warga sekitar.
Lalu bagaimana aturan main Dana Bagi Hasil (DBH) dari pertambangan panas bumi ini digelontorkan?
Jika merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 14 ayat 3.g secara jelas menyebutkan bahwa penerimaan dari pertambangan panas bumi yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dibagi dengan komposisi 20 persen untuk Pemerintah Pusat dan 80 persen untuk daerah.
Lebih lanjut, pembagian DBH dari penerimaan pertambangan panas bumi kepada daerah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
Merujuk pada ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH Panas Bumi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang dibagikan oleh pemerintah pusat.
Adapun ketentuan pembagian 80 persen DBH Panas Bumi untuk pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut: 16 persen untuk provinsi bersangkutan, 32 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 12 persen untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, 12 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama, dan 8 persen dialokasikan bagi kabupaten/kota yang memiliki fasilitas pengolahan panas bumi.
Namun, ketika data laporan keuangan pendapatan negara dari pertambangan panas bumi di Kabupaten Sukabumi ditelaah lebih lanjut, ditemukan adanya dugaan selisih anggaran realisasi yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Dari penghasilan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) panas bumi pada sektor pertambangan panas bumi yang begitu fantastis dengan nilai hingga ratusan miliar rupiah ditemukan kejanggalan yang mencolok pada dua komponen dana, yakni DBH.
Data ini diperoleh melalui perbandingan antara data realisasi Pemerintah Daerah (BPKAD Kabupaten Sukabumi) dan data realisasi DBH Panas Bumi yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.
Pada tanggal 22 Januari 2025, tim kami akhirnya mendapatkan laporan resmi terkait realisasi DBH sejak tahun 2020 hingga 2024 yang diperoleh langsung dari Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi. Namun, alih-alih memberikan jawaban yang menenangkan, data yang kami peroleh justru semakin mempertegas kesenjangan angka yang telah lama menjadi tanda tanya besar.
Misteri Angka dan Regulasi yang Tak Sejalan
Dari data di atas terdapat selisih angka realisasi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yang sangat fantastis, dimana di tahun 2020 realisasi penerimaan DBH memiliki selisih sebesar Rp.20.474.604.872 (Rp.20 Miliar,red), di tahun 2021 sendiri menyentuh selisih hingga Rp.151.607.909.604 (Rp.151 miliar, red), dan di tahun 2022 terdapat selisih Rp. 18.618.682.080 (Rp.18 miliar).
Sedangkan di tahun 2023 tidak ditemukanya angka selisih realisasi DBH dari pertambangan panas bumi yang sama sebesarnya Rp. 60.277.112.000. Sementara di tahun 2024 sendiri kami belum mendapat laporan audit BPK Kabupaten Sukabumi yang baru akan dirilis pada September 2025 mendatang.
Jika kita hitung, total selisih DBH berdasarkan yang dihimpun dari Tahun 2020 hingga 2023 sebesar Rp.190.701.196.556 (Rp.190 miliar,red). Lalu, bagaimana bisa ada selisih yang sangat signifikan dari dua data tersebut?
Saat dihubungi melalui saluran telepon pada Rabu, 12 Februari 2025, Iman Kabid BPKAD Kabupaten Sukabumi, menyebut bahwa adanya salah pencatatan dari pihaknya terkait selisih yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2023.
“Ya, mungkin salah pencatatan, jadi kita sebetulnya, jadi kita mah sekarang kendalinya koordinasinya dengan akuntansi (akuntansi BPKAD Kabupaten Sukabumi,red)," kata dia.
Ditambahkannya, pada tahun 2023 ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, dana yang seharusnya masuk ke kas daerah, sempat ditahan oleh kemenkeu dengan alasan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Jadi gini, di 2023 itu ada dana TDF (Treasury Deposit Facility,red), jadi dana yang seharusnya masuk ke kita khususnya di DBH, tapi sama kemenkeu dihold (tahan,red) dulu di BI (Bank Indonesia,red), kebijakannya seperti itu sekarang,” lanjutnya.
Iman melanjutkan bahwa untuk memastikan sinkronisasi data dan laporan keuangan daerah, pihak BPKAD akan mengacu pada sumber pencatatan data SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang dibuat oleh kementerian keuangan. Salah satu fungsi utama dari aplikasi ini adalah sebagai sistem informasi yang mencatat dana transfer yang masuk ke kas daerah.
"SIKD salah satu fungsinya merupakan sistem informasi dana transfer yang akan masuk ke kas daerah, kita bisa jadikan kendali realisasi dana transfer. Kalo untuk laporan keuangan daerah sendiri itu disusun oleh bidang akuntansi melalui laporan pertanggungjawaban yang nanti akan diperiksa oleh tim BPK. Biasanya SIKD diperlukan oleh BPK hanya untuk cek dan ricek dana yang masuk ke KasDa (Kas Daerah), itu juga kalo BPK minta" tutup Iman.
Di hari yang sama (Rabu, 12 Februari 2025,red) BPKAD Kabupaten Sukabumi melalui salah satu stafnya Hilda, memberikan revisi data realisasi DBH. Ditemukan adanya perbedaan di tahun anggaran 2023.
Ketika diwawancarai ulang, Iman memberikan revisi terbaru hingga tahun 2024. Hingga akhirnya, data realisasi DBH Panas Bumi memiliki angka kesamaan dengan data BPK yang didapat oleh kami.

Bonus Produksi Panas Bumi
Selain mendapatkan DBH dari panas bumi, daerah penghasil juga berhak menerima Bonus Produksi. (BP). Kebijakan ini ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2016 tentang Bonus Produksi Panas Bumi.
Dalam aturan tersebut, tepatnya di Pasal 3 Ayat 1, disebutkan bahwa:
- Bonus Produksi ditetapkan sebesar 1% dari pendapatan kotor hasil penjualan uap panas bumi.
- Jika panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik, maka bonusnya sebesar 0,5% dari pendapatan kotor hasil penjualan listrik.
Setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah daerah pun membuat aturan lanjutan untuk mengelola dana tersebut. Di Kabupaten Sukabumi, aturan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi No. 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bonus Produksi Panas Bumi.
Melalui aturan ini, dana dari hasil produksi panas bumi resmi dialokasikan untuk desa-desa yang terdampak serta program pembangunan daerah yang menjadi prioritas, pemerintah daerah menerima bonus produksi dari perusahaan panas bumi dan menyalurkannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kebijakan ini mulai dijalankan sejak tahun 2017, sementara di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kabandungan dan Kecamatan Kalapanunggal menjadi dua wilayah yang secara khusus berhak menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil panas bumi.
Pendapatan dari bonus produksi panas bumi harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya anggaran ini didasarkan pada pendapatan bonus produksi tahun sebelumnya yang sudah masuk ke rekening kas daerah.
Untuk pembagian dana, 50% dialokasikan ke desa-desa yang berada di kecamatan terdekat atau yang terkena dampak langsung dari proyek panas bumi. Desa yang menerima dana ini berada di Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal yang mencakup 13 desa. Sementara itu, 50% sisanya masuk ke kas pemerintah daerah dan digunakan untuk program pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pembagian dana ke desa dilakukan secara merata dan harus sesuai aturan yang berlaku. Pendapatan desa dari bonus produksi ini wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dikelola sesuai aturan keuangan desa.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menerima total pendapatan dari Bonus Produksi sektor panas bumi sebesar Rp 99.284.012.023 sejak tahun 2017 hingga 2024. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2018, dana bonus produksi ini harus digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaannya mencakup:
- Infrastruktur desa
- Pendidikan
- Kesehatan
- Perbaikan rumah tidak layak huni
- Pemberdayaan ekonomi
- Sarana keagamaan
- Pembangunan kantor desa
Mekanisme Pembayaran Bonus Produksi Pembayaran bonus produksi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Joint Operation Contract (JOC) dan setelah dimulainya produksi komersial. Proses pembayaran ini serupa dengan pembayaran izin eksploitasi sumber daya panas bumi, sehingga diklasifikasikan sebagai aset tetap yang akan didepresiasi sesuai jangka waktu JOC.
Alokasi Bonus Produksi Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 4 mengatur pembagian dana bonus produksi:
- 50% untuk desa dalam kecamatan terdekat dengan proyek panas bumi atau yang terdampak langsung.
- 50% untuk program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Ketidaksesuaian angka dan pertanyaan yang muncul pada tahun 2024, terjadi perbedaan alokasi bonus produksi hingga Rp 1 miliar.
Selain itu, terdapat penurunan signifikan dalam realisasi anggaran bonus produksi, yakni sekitar Rp 4 miliar dibandingkan tahun 2023. Namun, di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) justru mengalami peningkatan luar biasa hingga Rp 210.378.472.190.
Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi 13 desa di Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal yang mengalami fluktuasi penerimaan bonus produksi setiap tahunnya.
Perubahan Anggaran dalam Keputusan Bupati Sukabumi 2024 Dalam Lampiran Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900.1.3/Kep.872-BPKAD/2024 tanggal 12 November 2024, disebutkan bahwa terdapat penambahan alokasi bonus produksi untuk desa terdampak:
- Awalnya, setiap desa menerima Rp 307.692.308.
- Setelah perubahan, masing-masing desa mendapatkan Rp 461.538.462.
- Dengan demikian, ada tambahan Rp 153.846.154 per desa.
- Secara keseluruhan, total penambahan anggaran dari bonus produksi tahun 2024 mencapai Rp 2 miliar.
Perbandingan data anggaran dan ketidaksesuaian menurut data dari BPKAD Kabupaten Sukabumi, total anggaran Bonus Produksi (BP) tercatat sebesar Rp 10.128.100.427. Jika dibagi sesuai aturan, maka:
- 50% untuk Pemerintah Daerah = Rp 5.064.050.213
- 50% untuk 13 desa terdampak = Rp 5.064.050.213
Namun, dalam laporan terbaru, jumlah anggaran untuk dua kecamatan tersebut justru tercatat Rp 6 miliar, yang berarti ada tambahan Rp 1 miliar yang belum jelas sumbernya.
Sementara kini tim masih menunggu konfirmasi resmi ketidaksesuaian data ini yang menjadi perhatian tim. Untuk memastikan transparansi, tim masih menunggu klarifikasi dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sukabumi. Namun, informasi lebih lanjut baru bisa diperoleh setelah adanya koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DKIP).
Saat ditemui di kantor Desa Kabandungan beberapa waktu lalu, Bedi, Kades Kabandungan menyebut bahwa kewenangan desa dalam mengatur dan mengalokasikan dana - dana bantuan dari perusahaan seperti Bonus Produksi (BP) dan Dana Bagi Hasil (DBH), itu sangat terbatas bahkan tidak dapat berkutik sama sekali.
“BP ini kalau yang saya lihat itu hari ini masuk ke Kabupaten (pemerintah,red) dulu. Misalkan Rp.1 miliar, itu hanya 50% yang masuk ke 13 Desa yang ada di dua Kecamatan ini. Nah itu kita enggak semena - mena bisa menggunakan. Jadi SK (Surat Keputusan) sama “menu-nya” sudah ditentukan, ini buat pemberdayaan, ini buat fisik, buat apa, dan lain-lain,” ujarnya.
“Ini yang jujur secara pribadi cukup menyulitkan. Karena kalau hari ini dengan misalkan anggaran yang tidak begitu signifikan, teman-teman yang di lapangan, misalkan Desa saya nih 41 RT, 6 kadus, 12 RW gitu ya. Mereka juga ingin ada perubahan dengan penyerapan sumber anggaran itu, akhirnyakan proposal ini berlomba - lomba juga ke Desa. Padahal kita juga sudah mengerjakan sumber anggaran itu sudah sesuai dengan SK yang dibakukan sama Perbub (Peraturan Bupati) gitu sama udah ada “menu-nya” itu,” lanjutnya.
Bedi pun sempat mengajukan gagasannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi terkait dalam penggunaan Bonus Produksi.

Hal senada pun disampaikan oleh Kepala Desa Kalapanunggal, Dirja. Ia pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih adil dalam pembagian Bonus Produksi dan Dana Bagi Hasil yang dikucurkan perusahaan kepada Pemerintah.
“Tolong dibaginya jangan merata dong, dengan desa yang lain.Ini desa yang paling luas, desa yang paling banyak penduduk, terus ring satu, kok nilainya sama. Karena adil itu tidak harus sama,”tegasnya saat ditemui di ruangnya beberapa waktu lalu.
Melihat permasalahan yang ada di Desa Khususnya Kalapanunggal, Ketua DPK Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa) Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi sekaligus Kepala Desa Palasari Girang, Ujang Ma'mun, menuturkan bahwa selama ini Desa tidak pernah tahu menahu tentang perincian aliran dana Bonus Produksi dari Pemerintah.
”Kita kan tidak pernah tahu detail, kita hanya terima informasi bahwa BP itu semisal Rp. 2 miliar di tahun ini, tapi kan kita tidak pernah tahu bukti transferan dari BP ke Pemda itu bener gak Rp. 2 miliar,” ujar Ujang saat ditemui di Kantor Desa Palasari Girang beberapa waktu lalu.
“Lain halnya Dana Desa, ketika Dana Desa pagunya (sesuai,red) Rp 1 miliar semisal iitu kan disertai dengan beberapa bukti tuh, SK Kemenkeu, SK Kemendes, ini kan hanya sebatas tiba - tiba dapat informasi Rp 2 Miliar habis itu di SK-kan (Surat Keputusan,red),” lanjutnya.
Ujang pun berharap adanya transparansi besaran bukti transferan dari Perusahaan Star Energy ke Pemerintah Daerah.
Gurnadi Ridwan, Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menegaskan bahwa selisih dalam laporan anggaran daerah merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dalam wawancara via Google Meet, ia menjelaskan bahwa perbedaan angka ini sering kali muncul karena tahapan audit yang berbeda.
"Ya, sebenarnya sih selisih itu terkadang untuk audit itu satu hal yang lumrah saja, karena pertama kalau BPKD kan pasti akan menghitung berdasarkan realisasi yang kemudian mereka hitung berdasarkan updating gitu. Nah, kalau sudah masuk ke BPK biasanya itu adalah laporan yang hasil dari final yang dikirim oleh BPKD,” sampainya.
Namun, meskipun selisih ini bisa terjadi secara alami, bukan berarti hal tersebut harus diterima tanpa pertanyaan. Gurnadi menyoroti bahwa BPK memiliki Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai acuan dalam memverifikasi penggunaan anggaran. Standar ini mencakup berbagai pedoman, yang tertuang dalam Komponen SPKN Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP), PSP Nomor 100 tentang Standar Umum, PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.
Ketika selisih menjadi signifikan, hal ini bisa menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi sebenarnya. Gurnadi menekankan pentingnya melakukan konfirmasi lebih lanjut, bukan hanya kepada BPKD, tetapi juga kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
"Menurut saya sih bisa menjadi indikasi yang menarik ya, terkait tadi adanya laporan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," katanya.
Di balik angka-angka dalam laporan keuangan daerah, selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Apakah selisih ini benar-benar hanya bagian dari proses administrasi, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang perlu diperiksa lebih dalam? Transparansi dan akuntabilitas anggaran adalah kunci utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sebagaimana mestinya, tanpa celah bagi penyalahgunaan.

Lalu siapakah yang “bertanggung jawab” atas adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Wilayah Penghasil ? Ketika adanya dana bantuan dari sebuah perusahaan besar yang pendapatannya terus melonjak, sedangkan masyarakat sekitar terus berada di garis kemiskinan. Akankah “Masyarakat Penghasil” terus menjadi penonton sebuah panggung kemegahan perusahaan dan ketumpang tindihan dana - dana desa yang hanya menyasar pada kesejahteraan infrastruktur.

Menguji Keberlanjutan PLTP Gunung Salak
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak, salah satu proyek geothermal terbesar di Indonesia, kini berada di bawah kendali PT Star Energy Geothermal Indonesia (PT SEI), bagian dari konglomerasi raksasa Barito Pacific.
Sejak berpindah tangan dari Chevron Group pada tahun 2017, eksploitasi panas bumi di kawasan Gunung Salak terus berkembang dengan ekspansi pengeboran dan peningkatan kapasitas produksi listrik. Namun, di balik ekspansi ini, muncul pertanyaan besar tentang keberlanjutan proyek dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.
PT SEI adalah bagian dari Barito Pacific, perusahaan milik Prajogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes per Januari 2025. Sebagai Komisaris Utama PT Barito Pacific Tbk, Prajogo Pangestu dikenal sebagai pemain utama dalam industri petrokimia, kehutanan, dan energi terbarukan.
Perusahaan ini telah lama menerapkan strategi diversifikasi bisnis, termasuk masuk ke sektor panas bumi dengan mengakuisisi Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. pada tahun 2016 melalui perjanjian kredit senilai US$ 60 juta dengan Bangkok Bank Public Company Limited.
Akuisisi tersebut membawa Barito Pacific semakin dalam ke industri energi hijau, terutama di sektor panas bumi yang disebut-sebut sebagai masa depan energi terbarukan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, menjadikannya lahan strategis bagi korporasi untuk memperluas bisnis energi bersih. Dengan 115 sumur produksi yang menghasilkan daya sebesar 377 MW, PLTP Gunung Salak menjadi aset penting dalam portofolio bisnis PT SEI.
Meski PLTP Gunung Salak diklaim sebagai sumber energi bersih, eksploitasi panas bumi tidak terlepas dari isu lingkungan. Kawasan operasi pembangkit ini berada dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna.
Perluasan sumur produksi hingga 2025 dengan target kapasitas 495 MW memunculkan kekhawatiran mengenai perubahan ekosistem dan keseimbangan hidrologi di sekitar wilayah operasional. Di samping itu, aktivitas pengeboran yang masif menimbulkan pertanyaan mengenai dampak seismik yang mungkin terjadi.

Gempa Bumi Menghantui Masyarakat Sekitar Proyek Panas Bumi
Selain wilayah Sukabumi aktivitas proyek panas bumi juga dikeluhkan oleh warga di wilayah Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kondisi sosial ekonomi masyarakat umumnya berada di bawah tingkat menengah. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh, dengan jumlah pengusaha yang sangat terbatas. Keberadaan perusahaan panas bumi di wilayah ini memberikan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif.
Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat antara lain adalah berkurangnya sumber air akibat aktivitas perusahaan. Bambang salah satunya sebagai Kepala Dusun Purwabakti, ia mengeluhkan bahwa pasokan air menjadi lebih kecil dan tidak stabil. Selain itu, aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pergerakan tanah dan gempa bumi.
"Kalau pengeboran sudah mulai, kita sering merasa ada getaran. Bahkan pernah ada kejadian gempa yang cukup terasa di awal tahun 2024," ujar Bambang.
Berdasarkan catatan masyarakat, gempa dengan skala 4 hingga 5 pernah terjadi, dan dalam satu minggu setidaknya ada satu kali getaran yang dirasakan.
Di sisi lain, perusahaan panas bumi juga memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk bonus produksi yang disalurkan ke desa melalui pemerintah daerah. Dana yang diterima Desa Purwabakti pada tahun 2024 mencapai Rp740 juta per tahun, yang dibagi dalam dua tahap, yaitu 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua.
Dana bonus produksi tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti rehabilitasi kantor desa serta pengerasan jalan di RW 8, Dusun 4, dengan panjang 700 meter dan lebar 3 meter.
Namun, beberapa warga mengungkapkan bahwa distribusi bantuan masih dirasa kurang maksimal. "Kalau dihitung-hitung, memang ada bantuan, tapi kalau dibandingkan dengan dampak yang kami rasakan, rasanya belum cukup," keluh Bambang.
Masih diceritakan Bambang, selain dampak terhadap air dan potensi gempa, kebisingan dari aktivitas perusahaan juga menjadi keluhan utama. Saat proses drilling atau pembuangan panas bumi dilakukan, suara gemuruh yang menyerupai ombak besar dapat terdengar hingga dusun yang lebih jauh.
Terkait dengan klaim ramah lingkungan, beberapa warga mengaku tidak sepenuhnya setuju.
"Dampaknya masih ada, terutama terkait dengan getaran dan kondisi tanah yang labil. Kami takut terjadi longsor karena kondisi tanah di sini berbukit," ujarnya.
Meskipun ada dampak negatif, masyarakat juga memahami bahwa keberadaan perusahaan ini dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat luas untuk penyediaan listrik. "Kami di sini memang saling membutuhkan, tapi dampaknya lebih terasa di lingkungan kami," pungkasnya.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, masyarakat berharap adanya solusi terbaik agar keberadaan perusahaan panas bumi tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan sekitar.
Sementara itu menurut Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Bandung Virga Librian, Senin Pagi, 9 Desember 2024, kegiatan di titik PLTP memang dapat terasa seperti gempa yang memang tidak sebesar gempa tektonik pada umumnya.
“Kalau yang dekat dengan sumber di Gunung Salak , mungkin bisa jadi akibat yang Citarik sebagai bukti seismisitasnya itu. Tetapi, itu masih belum bisa kita konfirmasi. Karena bisa jadi juga itu akibat dari itu tadi, (gempa) buatan, sebagai output dari buatan karena kita, lalu alam. Geothermal itu juga bisa jadi sebagai source terjadinya gempa bumi,” jelasnya saat ditemui tim di kantor BMKG Klas 1 Bandung.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi panas bumi dapat memicu aktivitas gempa mikro, meski masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan korelasinya di kawasan Gunung Salak.
Keuntungan Besar di Balik Investasi Geothermal
PT Star Energy Geothermal Indonesia bukan hanya sekadar perusahaan energi terbarukan, tetapi juga sebuah entitas bisnis yang mengelola keuntungan besar. Hendra Soetjipto Tan, Direktur Utama PT SEI, tercatat memiliki lembar saham sebanyak 108.900 unit atau setara 10,89 miliar rupiah berdasarkan laporan usaha per 20 Juli 2023. Angka ini menunjukkan betapa besar nilai ekonomi yang berputar di sektor geothermal.
Di sisi lain, komitmen Star Energy untuk berkontribusi pada masyarakat masih menjadi pertanyaan besar. Meskipun dalam laman resmi perusahaan disebutkan adanya program tanggung jawab sosial (CSR), dampak konkret terhadap masyarakat sekitar belum sepenuhnya terpantau. Sebagian warga di sekitar kawasan operasi PLTP Gunung Salak masih mempertanyakan sejauh mana manfaat langsung dari proyek ini bagi mereka, baik dalam bentuk kesejahteraan ekonomi maupun perlindungan lingkungan.
Dalam konteks lebih luas, pemanfaatan panas bumi merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) 2060. Namun, tanpa regulasi ketat dan pengawasan yang transparan, eksploitasi besar-besaran dapat berujung pada dampak lingkungan yang sulit dikendalikan.
Dengan ekspansi yang terus dilakukan oleh PT SEI, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawal perkembangan proyek ini agar tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan. Apakah investasi besar ini benar-benar ditujukan untuk kebaikan bersama, atau sekadar menjadi ladang keuntungan bagi segelintir elit bisnis.
Janji Kemajuan yang Tak Kunjung Terwujud
Sejak eksploitasi panas bumi mulai beroperasi, berbagai janji mengenai peningkatan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur telah digaungkan oleh pemerintah dan perusahaan pengelola. Namun, data kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa manfaat dari proyek-proyek besar ini tidak didistribusikan secara merata.
Lapangan pekerjaan yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal justru lebih banyak diberikan kepada tenaga kerja dari luar daerah dengan keahlian khusus. Warga sekitar hanya mendapatkan pekerjaan musiman atau pekerjaan dengan upah rendah yang tidak mampu mengangkat kesejahteraan mereka secara signifikan. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin nyata di tengah pertumbuhan industri panas bumi yang pesat.
Perusahaan pengelola proyek panas bumi kerap membanggakan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Namun, apakah kontribusi tersebut benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat lokal? Hingga saat ini, banyak warga yang masih hidup dalam keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur di beberapa wilayah juga masih minim, menandakan bahwa dampak pembangunan dari eksploitasi panas bumi tidak serta-merta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
Panas bumi memang digadang-gadang sebagai energi bersih dan ramah lingkungan, tetapi eksploitasi yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat justru memperlihatkan sisi lain dari proyek ini. Sumber daya alam yang dieksploitasi seharusnya tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi segelintir elit bisnis, tetapi juga harus mampu mengangkat kehidupan masyarakat yang selama ini berada di garis kemiskinan.
Data kemiskinan yang tinggi di Kabandungan dan Kalapanunggal menjadi bukti bahwa ada yang belum beres dalam sistem distribusi manfaat dari proyek-proyek besar seperti eksploitasi panas bumi. Jika pemerintah dan perusahaan energi serius ingin menjadikan panas bumi sebagai energi yang berkelanjutan, maka mereka harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi juga berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, serta pembangunan infrastruktur yang merata harus menjadi prioritas. Masyarakat setempat tidak boleh terus menjadi penonton dalam proyek-proyek besar di wilayah mereka sendiri.
Jika tidak ada perubahan nyata dalam kebijakan dan distribusi manfaat ekonomi, maka eksploitasi sumber daya alam hanya akan menjadi bentuk baru dari ketimpangan sosial yang semakin tajam. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya menjadi berkah bagi semua, bukan hanya bagi segelintir pihak yang menguasainya.
Hingga berita ini dimuat, kami masih menunggu konfirmasi dari Perusahaan Star Energy, terkait transparansi pendapatan dari laba kotor penjualan gas dan uap panas bumi, yang sangat berkorelasi dengan pendapatan negara yang bermuara pada masyarakat penghasil panas bumi. (END) ###
Catatan Editor : reportase ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media. Diantaranya Pikiran Rakyat, Bandung Bergerak, Independen.id sebagai bagian dari program Mengawasi Proyek Strategis Nasional yang didukung AJI Indonesia dan Kurawal Foundation.