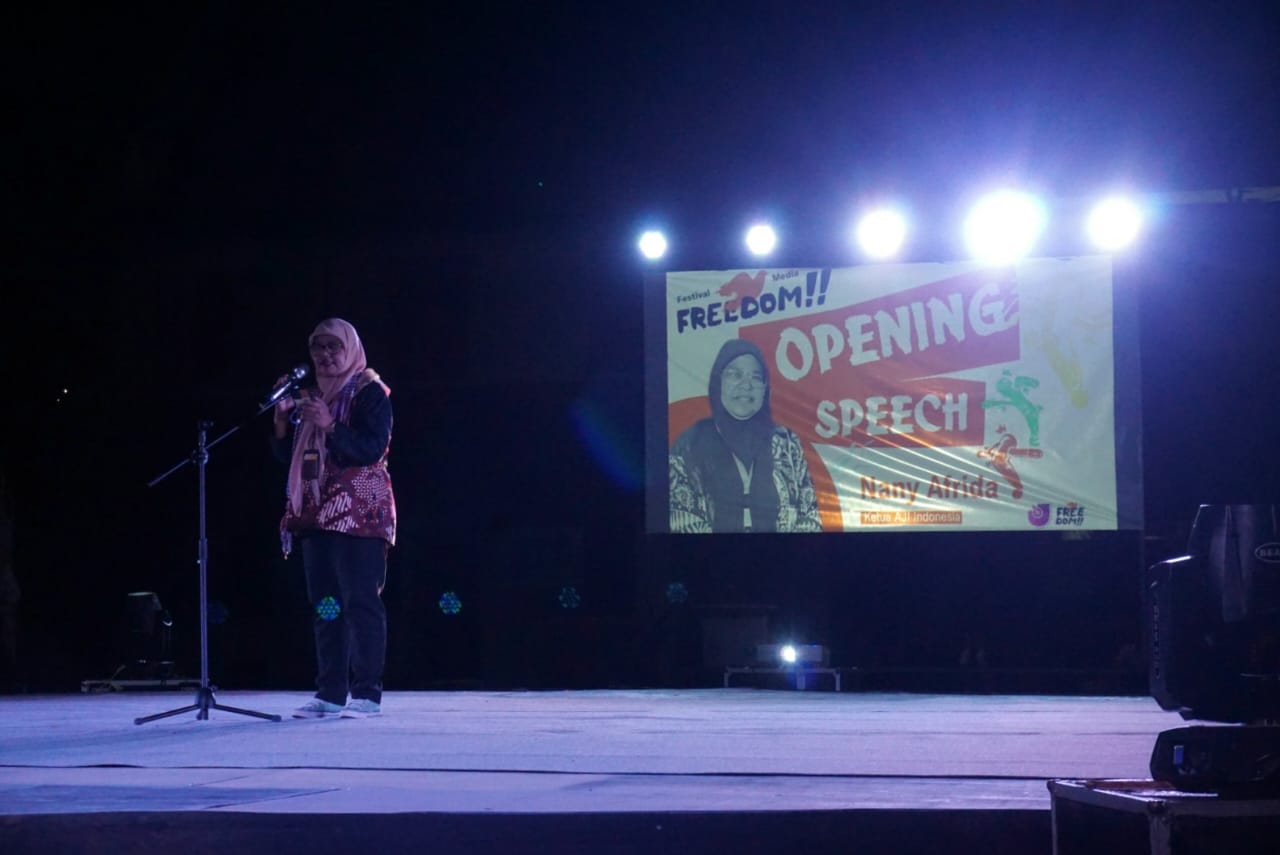Penulis: Anza Suseno
Independen.id – Lampu operasi menyorot tubuh pasien yang terbaring di meja tindakan. Suara monitor detak jantung berpadu dengan bunyi alat medis yang bekerja tanpa henti, menciptakan irama tegang di dalam ruang cath lab RSUD Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Udara yang bercampur aroma antiseptik menusuk hidung, sementara paparan radiasi tinggi menjadi risiko rutin bagi para petugas medis.
Di balik masker hijau steril, sorot mata dokter dan perawat tak lepas dari layar monitor. Mereka sedang berpacu dengan waktu, menghadapi detik-detik krisis penyelamatan nyawa. Kamis pagi, 31 Juli 2025 itu, suasana di ruang tindakan terasa tegang sekaligus dipenuhi harapan.
Di antara tim medis, sosok dr. Fadjar Herianto, dokter ahli penyakit jantung intervensi. Dengan tenang, ia menatap layar monitor, menelusuri jalur pembuluh darah pasien yang tersumbat. Jarum-jarum halus dan kawat pandu diarahkan untuk menemukan titik penyumbatan. Pada momen yang tepat, ring dipasang, membuka kembali aliran darah yang sempat terhenti.
Bagi dr. Fadjar, momen seperti itu bukan hal asing. Hampir setiap hari ia harus berhadapan dengan salah satu pembunuh terbesar masyarakat Indonesia: penyakit jantung.
Operasi jantung di rumah sakit tempat dr. Fadjar bertugas hanya bisa dilakukan dalam waktu terbatas, antara 15 hingga 30 menit, dan maksimal 1 hingga 2 jam.
Keterbatasan alat membuat rumah sakit tidak dapat menangani operasi yang lebih krusial, sehingga pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan standar peralatan yang lebih lengkap.
“Untuk satu pasien kurang lebih membutuhkan waktu 15 sampai 30 menit, maksimal 1 sampai 2 jam. Saya tidak mengerjakan operasi yang sifatnya krusial karena berkaitan dengan keterbatasan alat yang kita miliki. Jadi pasien yang membutuhkan standar lebih tinggi harus dirujuk, dan itu yang kami lakukan,” ujar dr. Fadjar.
Sepulang bertugas dari Australia dan sempat berkarier di salah satu rumah sakit besar di Jakarta, dr. Fadjar, seorang ahli penyakit jantung, tak pernah menyangka di Sukabumi, sebuah kota kecil di Jawa Barat, beban kerjanya akan seberat ini. Ia mengira tinggal di kota kecil dengan masyarakat yang tampak patuh akan membuat pekerjaannya lebih ringan. Namun kenyataan berkata lain.
“Pertama kali saya tugas di sini, saya pikir saya tidak akan mengalami beban. Karena melihat ini kota kecil, masyarakatnya juga relatif patuh-patuh. Nyatanya berbeda, berbanding terbalik,” ujar dr. Fadjar.
Angka kejadian penyakit jantung di Sukabumi terus meningkat. Hampir tiap hari ia melakukan tindakan penyelamatan nyawa. Menurut pengakuannya, dalam satu malam saja bisa ada dua hingga tiga pasien darurat yang harus ditangani dengan tindakan primary PCI atau rescue PCI. Hampir seminggu penuh jadwalnya padat oleh pasien jantung.
“Hampir tiap hari saya mengerjakan tindakan. Sebuah kota kecil dengan populasi cuma 300 ribu, tapi kasusnya sangat tinggi. Kadang dalam satu hari bisa 10 sampai 15 pasien. Sampai sekarang saya bahkan belum merasakan keleluasaan waktu untuk keluarga atau sekadar hobi,” tuturnya.
Benar saja, berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, jumlah peserta JKN penderita penyakit dalam seperti jantung mencapai 8.000 jiwa. Angka itu masih mendominasi beban pembiayaan kesehatan di wilayah Sukabumi, dengan total biaya sudah menembus Rp20 miliar hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025.
Data ini menegaskan, penyakit jantung masih menjadi penyakit tidak menular dengan pembiayaan tertinggi. Dr. Fadjar menjelaskan, penyakit jantung tidak muncul tiba-tiba, dapat dimulai sejak bayi hingga remaja. Kebiasaan hidup dan pola makan sangat mempengaruhi kondisi pembuluh darah.
Selama ini ia menduga faktor utama di Sukabumi adalah kebiasaan merokok. Namun belakangan, ia menaruh perhatian besar pada ancaman lain, yaitu lemak trans.
Lemak trans memberi kontribusi besar terhadap kerusakan pembuluh darah. Zat ini meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat, menurunkan HDL atau kolesterol baik, serta mempercepat terbentuknya plak yang menyumbat aliran darah. Jika plak pecah, serangan jantung atau stroke bisa terjadi.
“Tadinya saya pikir masalahnya hanya rokok. Tapi kemudian saya melihat ancaman lebih besar datang dari lemak trans. Karena lemak trans meningkatkan LDL, menurunkan HDL, dan proteksi tubuh pun hilang. Akibatnya, plak menumpuk dan bisa pecah, menutup aliran darah,” jelas dr. Fadjar.
Sementara angka kasus serangan jantung di Indonesia sendiri semakin memprihatinkan, bahkan kini mengincar usia produktif.
Dr. Fadjar mengungkapkan pengalamannya menangani pasien termuda yang baru berusia 20 tahun. Pasien tersebut adalah seorang mahasiswa yang tidak memiliki riwayat merokok, namun mengalami serangan jantung akibat tumpukan plak di pembuluh darahnya.
“Pasien saya termuda adalah 20 tahun. Dia baru saja masuk kuliah, tidak merokok, bersih. Tapi kemudian terkena serangan jantung. Setelah diperiksa, ada bentukan plak di salah satu pembuluh darah jantung. Akhirnya kami pasang cincin di sana,” kata dr. Fadjar.
Di balik angka statistik yang kerap terdengar kaku, ada wajah-wajah nyata yang berjuang melawan penyakit mematikan. Salah satunya Herlansyah, seorang guru berusia 56 tahun, warga Sukabumi.
Pada waktu itu, nuansa pagi cerah dengan jarum jam menunjuk pukul 05.30, Selasa, 13 Mei 2025. Di rumah sederhana milik Herlansyah di Sukabumi terasa tenang. Seperti biasanya, ia duduk di ruang keluarga ditemani secangkir kopi hangat dan berita pagi di televisi. Semuanya tampak biasa saja, tanpa tanda bahaya. Namun di balik ketenangan itu, sebuah titik balik besar dalam hidupnya tengah menanti. Tiba-tiba tubuhnya memberi sinyal yang tak biasa.
“Pagi itu habis ngopi, saya kira biasa aja,” kenang Herlansyah. “Tapi badan makin nggak enak. Saya muntah, keluar keringat dingin, dada terasa sesak. Sakitnya bukan di sebelah kiri, tapi tepat di tengah. Keringat dingin nggak berhenti.”
Istrinya, yang saat itu berada di dapur, mendapati suaminya pucat pasi. Panik dan cemas bercampur jadi satu.
“Saya lihat wajahnya putih sekali, dingin, dan dia kesakitan. Saya langsung takut kehilangan,” ucap sang istri dengan suara bergetar.
Dalam kondisi kalut, ia segera meminta bantuan keluarga dan membawa Herlansyah ke rumah sakit. Di rumah sakit, hasil elektrokardiogram (EKG) menunjukkan kondisi serius. Pembuluh darah jantungnya tersumbat hampir seratus persen di tiga titik sekaligus.
“Hasil EKG kata dokter itu hampir 100 persen ada pembuluh darah yang tersumbat. Salah satunya karena sumbatannya ada tiga katanya. Cuma yang serangan itu, yang jantung sebelah kanan apa, apa sebelah kanan pokoknya. Itu hampir 100 persen tersumbatnya itu. Saya masuk ICU, menurut dokter saya harus dipasang ring untuk membuka penyumbatan darah itu. Ya saya langsung oke, siap diring,” ungkapnya.
Sore harinya, pada pukul 17.00 WIB, dokter memutuskan tindakan cepat pemasangan ring. Herlansyah sempat tertegun, merasa tak percaya, namun ia tahu tak ada pilihan lain.
“Dokter bilang kalau tidak dipasang ring, saya bisa terus sakit. Jam lima sore saya masuk ruang operasi, dan syukurlah operasi berjalan lancar.”
Serangan jantung itu menjadi titik balik hidup Herlansyah. Dulu ia merasa sehat, masih kuat mengajar, dan aktif mendampingi keluarga. Tetapi kenyataan berkata lain.
“Saya sering makan malam gorengan, nasi goreng, mie instan. Kadang habis makan langsung tidur. Kolesterol saya abaikan. Ternyata kebiasaan itu yang akhirnya jadi bumerang,” ujarnya.
Ancaman Tersembunyi di Balik Makanan Olahan
Peristiwa serangan jantung hingga proses hidup dan mati di ruang operasi seringkali membuat kita kembali merenungkan hal sederhana: apa yang kita makan setiap hari. Sedikit saja melenceng dari pola makan sehat, besar kemungkinan tubuh sudah terpapar lemak trans.
Zat berbahaya ini sama mematikannya seperti terdengar. Lemak buatan hasil industri diciptakan bukan untuk kesehatan manusia, melainkan memperpanjang umur simpan makanan.
Di banyak negara, lemak trans sudah dilarang. Namun di Indonesia, zat ini masih dengan mudah ditemukan, mulai dari gorengan di pinggir jalan, biskuit dalam kemasan, hingga berbagai makanan olahan yang sering kita konsumsi tanpa sadar. Padahal resikonya sangat besar: menyumbat arteri dan memicu meningkatnya angka penyakit jantung.
Lantas, apa itu lemak trans?
Anda mungkin belum familiar dengan istilah trans fatty acid atau asam lemak trans. Secara sederhana, ini adalah asam lemak tidak jenuh yang berasal dari dua sumber: alami dan industri. Yang paling berbahaya adalah lemak trans industri, hasil dari proses hidrogenasi pada minyak nabati.
Proses ini membuat minyak cair berubah menjadi padat, dikenal sebagai partially hydrogenated oil (PHO). Tanpa disadari, banyak dari kita mungkin sudah mengkonsumsinya setiap hari. Lemak trans ditemukan pada abad ke-20 untuk menggantikan mentega dengan harga murah sekaligus memperpanjang umur simpan. PHO digunakan untuk menggoreng serta sebagai bahan membuat kue dan roti.
Lemak trans terbukti mengubah kadar kolesterol, meningkatkan LDL (kolesterol jahat) yang menyumbat pembuluh darah, sekaligus menurunkan HDL (kolesterol baik) yang melindungi jantung. Kondisi ini mempercepat aterosklerosis atau penumpukan plak di arteri, yang bisa berujung pada serangan jantung maupun stroke.
Lemak trans adalah yang “paling jahat”
Dokter penyakit dalam, Muhammad Arzan Alfarish, Sp.PD., menegaskan bahwa tubuh memang membutuhkan lemak, tetapi tidak semua lemak bersifat baik.
“Ada beberapa jenis asam lemak atau kolesterol yang bisa merugikan kesehatan, dan itu yang harus kita hindari. Lemak trans adalah yang paling jahat di antara semuanya,” jelasnya.
Arzan kemudian membagi asam lemak menjadi tiga kelompok utama. Pertama, asam lemak jenuh, yang umumnya banyak ditemukan pada daging merah. Jenis lemak ini, jika dikonsumsi berlebihan, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Kedua, asam lemak tidak jenuh, yang lebih banyak berasal dari tumbuhan, misalnya pada minyak zaitun (olive oil) atau alpukat. Jenis lemak ini dikenal lebih sehat dan bermanfaat bagi tubuh.
Ketiga, asam lemak trans. Pada awalnya, kelompok ini juga termasuk ke dalam asam lemak tidak jenuh. Namun setelah melalui proses industrialisasi seperti hidrogenasi pada minyak nabati agar lebih awet, lemak tersebut berubah menjadi bentuk yang berbahaya bagi tubuh. Dampaknya pun tidak main-main.
“Lemak trans ini terbukti meningkatkan LDL sekaligus menurunkan HDL. Kalau HDL turun dan LDL naik, itu sangat berbahaya. Kondisi itu bisa mempercepat terjadinya aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah,” tambah Arzan.
Lebih jauh, Arzan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai makanan sehari-hari.
“Sebisa mungkin kita harus menghindari trans fatty acid. Bentuknya banyak pada makanan olahan seperti biskuit atau cookies. Tapi yang paling sering kita jumpai adalah gorengan.
Pada awalnya minyak itu baik, unsaturated fatty acid. Tapi kalau dipakai berulang kali dan dipanaskan terus, yang terbentuk justru trans fat. Trans fat itu akan melekat pada makanan yang digoreng, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan,” tegasnya.
Serangan jantung di banyak kasus yang terus meningkat di Indonesia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi lemak trans yang hingga kini masih sulit dikendalikan.
WHO sejak 2018 telah menyerukan eliminasi total lemak trans industri pada tahun 2023 melalui strategi REPLACE. Hingga saat ini, sudah ada 53 negara yang menerapkan kebijakan tersebut, baik dengan melarang penggunaan partially hydrogenated oils (PHO) maupun membatasi kandungannya maksimal 2 persen dari total lemak dalam produk pangan.
Posisi Indonesia Indonesia baru mewajibkan produsen mencantumkan kandungan TFA dalam label nutrisi. Sumber : WHO
Namun, Indonesia masih tertinggal. Hingga kini, belum ada regulasi khusus yang secara tegas melarang atau membatasi kadar lemak trans industri. Aturan yang ada baru sebatas kewajiban pencantuman informasi gizi pada label makanan.
Penelitian Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center IPB University bersama WHO pada 2023 memperkuat kekhawatiran ini. Dari 130 sampel pangan olahan di Jakarta dan Bogor, ditemukan 11 produk atau 8,64 persen mengandung lemak trans di atas 2 persen dari total lemak melampaui batas rekomendasi WHO.
Produk dengan kadar tinggi ditemukan pada berbagai makanan, mulai dari margarin, shortening, biskuit, pai, wafer berkrim coklat, red velvet cake, roti maryam, martabak cokelat, croissant isi coklat, hingga danish pastry.
Analisis lebih lanjut menunjukkan, 8 persen atau 10 produk memiliki kadar trans fatty acid (TFA) lebih dari 2 gram per 100 gram lemak. Bahkan, sekitar 3 persen produk atau 4 sampel tercatat mengandung TFA lebih dari 0,5 gram per porsi jumlah yang seharusnya wajib dicantumkan pada label sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2021.
Temuan ini menjadi alarm serius. Lemak trans terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung dan kematian. WHO mencatat, setiap tahun sekitar 500 ribu orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskular yang dipicu konsumsi lemak trans.
Beban Kesehatan dan Anggaran Negara
Meskipun demikian, angka kematian akibat penyakit yang dipicu oleh konsumsi lemak trans, seperti jantung koroner, masih menempati posisi tertinggi di Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga membebani anggaran negara.
Data Kementerian Kesehatan mencatat, pada 2023, pembiayaan penyakit katastropik melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp. 34,8 triliun. Dari jumlah tersebut, penyakit kardiovaskuler meliputi jantung dan stroke mendominasi dengan total pembiayaan sebesar Rp. 22,8 triliun, menjadikannya pos terbesar dalam pengeluaran JKN untuk penyakit katastropik.
Lebih rinci, Kemenkes mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 20 juta kasus penyakit jantung di Indonesia, dengan pembiayaan tertinggi mencapai Rp. 17,6 triliun. Hal ini menegaskan bahwa penyakit jantung masih menjadi beban terbesar dalam sistem kesehatan nasional.
Reformulasi Jadi Langkah Awal
Kementerian Kesehatan mengakui, eliminasi lemak trans perlu dilakukan untuk menekan penyakit jantung yang menjadi penyakit dengan pembiayaan tertinggi dalam JKN. Namun sejauh ini, kebijakan yang ditempuh masih sebatas pada reformulasi kadar lemak trans yang banyak terkandung dalam makanan siap saji maupun produk industri.
“Baking fat, kemudian biskuit, kemudian di martabak, itu banyak tuh loh ya, croissant gitu ya, itu makanan-makanan yang banyak mengandung lemak transnya, dan itu biasanya cukup tinggi tuh kadar-kadarnya ya. Nah, kalau kita lihat apa yang kita lakukan dalam melakukan kebijakan yang pasti memang diharapkan adanya reformulasi ya, jadi mengurangi adanya lemak trans tadi. Yang kemudian juga kita harus pastikan labeling ya, adanya labeling misalnya kalau kadar lemaknya ketinggian, itu harus diturunkan,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes RI.
Kemenkes menekankan bahwa langkah reformulasi dan labeling menjadi tahap awal sebelum kebijakan eliminasi lemak trans diberlakukan secara penuh. Diharapkan, jika regulasi lebih ketat segera diimplementasikan, Indonesia mampu menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular sekaligus mengurangi beban pembiayaan negara yang terus meningkat setiap tahunnya.
Regulasi Lemak Trans Masih Tertahan
Meskipun konsumsi lemak trans terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, hingga kematian dini akibat penyakit kardiovaskular, WHO bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi global agar setiap negara menghapus peredaran lemak trans industri dari rantai pasok pangan.
Namun hingga kini, Indonesia masih tertinggal. Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur eliminasi lemak trans industri. Padahal, tercatat sudah ada 53 negara di dunia yang menerapkan kebijakan tegas, termasuk Singapura dan Thailand yang lebih dulu melindungi warganya dari ancaman ini.
WHO menawarkan dua opsi kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah:
1. Membatasi kandungan lemak trans maksimal 2 persen dari total kandungan lemak pada semua makanan.
2. Atau melarang total produksi, impor, penjualan, dan penggunaan partially hydrogenated oils (PHO) pada seluruh produk pangan.
Selain itu, WHO juga mendorong produsen makanan berhenti menggunakan PHO dalam proses produksi agar inovasi pangan tetap berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Berkaca pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2021, setiap produk pangan yang mengandung lemak trans seharusnya wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label kemasan. Namun temuan di lapangan menunjukkan masih banyak produk yang belum transparan terhadap konsumen. Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa lemak trans masih beredar luas di pasaran dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Tarik ulur regulasi semakin terlihat ketika rancangan aturan teknis mengenai kewajiban pencantuman kadar lemak trans masih tertahan di meja birokrasi. Proses uji publik sudah dilakukan, tetapi pengesahannya belum rampung karena perbedaan pandangan antar-kementerian serta keberatan dari pelaku usaha.
Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa regulasi terkait lemak trans sangat penting untuk segera diatur.
“Jadi kesimpulannya ini memang perlu diatur. Itulah yang mewadahi kenapa undang-undang ini berbicara di Peraturan Pemerintah Nomor 28 untuk ini harus diatur. Dan yang berhak mengatur itu adalah Badan POM. Dan kita sekarang lagi proses menyelesaikan draft-nya. Draft-nya sebetulnya sudah kita lakukan uji publik, kita lakukan harmonisasi, dan sebetulnya sudah diproses,” ujarnya.
Namun, Taruna mengakui masih ada sejumlah kendala dalam penerapannya, terutama dari kalangan industri.
“Masih ada kendala khususnya di pelaku usaha. Karena tentu mereka harus melakukan rebranding, reformulasi, dan perubahan konten produk-produknya, dan itu butuh biaya. Sementara proses keluarnya aturan itu tidak mudah, kita tidak bisa otoriter,” tegasnya.
Taruna menambahkan, proses harmonisasi tidak hanya menyangkut urusan kesehatan, tetapi juga sektor perdagangan yang erat kaitannya dengan kepentingan pelaku usaha.
“Antar lembaga misalnya, peraturan Badan POM yang akan dikeluarkan sebagai pelaksanaan teknis akan berdampak pada sistem perdagangan. Karena itu, kami harus melakukan harmonisasi dengan Kementerian Perdagangan. Di sana ada banyak pelaku usaha di bawahnya, sehingga tentu tidak mudah. Kalau yang berhubungan dengan aspek kesehatan, biasanya lebih sederhana, karena satu visi dengan Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Ia menegaskan, aturan khusus mengenai lemak trans hingga kini masih terjebak dalam proses harmonisasi lintas sektor. Padahal, drafnya sudah lama disusun oleh BPOM. Regulasi yang seharusnya menjadi pelindung kesehatan publik justru tertahan karena tarik-menarik kepentingan, terutama dari sisi perdagangan dan industri pangan. Situasi ini membuat masyarakat tetap terpapar risiko penyakit jantung akibat lemak trans, sementara negara belum memiliki payung hukum yang tegas untuk membatasinya.
“Setelah itu, nanti juga harus ada harmonisasi dengan masyarakat langsung. Saat ini, aturan kami tentang gula, garam, dan lemak sudah disusun dan diselesaikan tim kami. Namun, ada beberapa poin yang tidak disetujui Kementerian Perdagangan sehingga perlu diulang, dengan tetap melibatkan para pelaku usaha,” lanjutnya.
Perlindungan Konsumen Masih Tertahan
Secara regulasi, BPOM memiliki mandat kuat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah menegaskan posisi BPOM sebagai otoritas tunggal dalam pengawasan keamanan pangan.
Namun implementasi aturan penting, seperti kewajiban pencantuman kadar lemak trans di label makanan, masih belum berjalan. Tarik ulur kepentingan industri dan harmonisasi antar-kementerian membuat upaya perlindungan konsumen tertahan.
Akibatnya, masyarakat masih menghadapi risiko serius dari konsumsi lemak trans yang tersembunyi di berbagai produk pangan sehari-hari. Tanpa langkah konkret, ancaman penyakit jantung, stroke, hingga diabetes diprediksi akan terus menghantui jutaan warga Indonesia.
Selain itu hingga kini, aturan mengenai lemak trans di Indonesia dinilai masih longgar. Belum ada kewajiban tegas bagi produsen untuk mencantumkan kadar lemak trans di kemasan pangan. Akibatnya, konsumen tidak sepenuhnya terlindungi dari ancaman penyakit jantung, stroke, maupun diabetes yang berhubungan erat dengan konsumsi lemak berbahaya ini.
Padahal, label pangan bukan sekadar formalitas. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), label adalah bentuk objektivitas produsen dalam memberikan informasi jujur kepada konsumen.
“Kalau terjadi perubahan label, karena kan yang atur seluruh label yang ada di makanan itu Badan POM. Ada peraturannya dan ada undang-undangnya juga. Kita diberikan otoritas untuk mengatur. Makanya cek klik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kita yang ngatur. Itu semua tercantum di labelnya. Dan di labelnya itulah menunjukkan objektivitas,” tegas Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.
Taruna menegaskan, setiap bentuk manipulasi label adalah pelanggaran serius. Produsen yang terbukti mengganti atau memalsukan label tanpa izin ulang bukan hanya berisiko ditarik produknya dari peredaran, tetapi juga dapat menghadapi sanksi hukum berat.
“Kalau ada pelanggaran misalnya, dia tidak mengajukan label ulang, lantas di lapangan dia ganti label itu. Itu namanya fraud, pemalsuan. Bisa ada hukuman berlapis, produk bisa ditarik, dimusnahkan, bahkan orangnya juga bisa kena sanksi hukum sampai 12 tahun penjara,” ujar Taruna menekankan.
Di tengah kritik bahwa regulasi kerap dianggap memberatkan, BPOM menegaskan aturan justru dibuat untuk melindungi konsumen, bukan menghambat industri.
“Industri itu kan sebuah usaha dan usaha itu berniat untuk mendapat untung. Untung tidak dilarang. Tetapi jangan melanggar hukum dengan melakukan penipuan kepada konsumen. Yang kedua, pelaku usaha punya tanggung jawab menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumennya,” lanjut Taruna.
Ia mengingatkan, edukasi publik soal bahaya lemak trans adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Industri juga memiliki kewajiban moral agar tidak menutup mata terhadap risiko kesehatan masyarakat.
“Kalau konsumen selalu makan begitu, ujung-ujungnya akan sakit. Nanti dampaknya, dia tidak akan bisa lagi menggunakan barangnya. Jadi kan akhirnya dia rugi sendiri juga,” tambahnya.
Kelonggaran aturan lemak trans membuat perlindungan konsumen di Indonesia belum sepenuhnya kokoh. Sementara tarik ulur kepentingan antar kementerian dan industri membuat langkah Indonesia untuk membebaskan masyarakat dari ancaman lemak trans semakin lambat.
Di saat banyak negara sudah bergerak cepat sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menghapus lemak trans dari rantai pangan, Indonesia masih berkutat pada perdebatan regulasi.
Tanpa aturan tegas, konsumen tetap berada di posisi rentan tak sadar berapa banyak lemak trans yang masuk ke tubuh setiap kali membeli produk olahan.
Putar Balik Dampak Lemak Trans
Setelah serangan jantung yang hampir merenggut nyawanya, Herlansyah kini menjalani hidup dengan cara berbeda. Dua kali operasi besar menjadi titik terendah yang membuatnya meninggalkan pola makan yang tidak sehat gorengan, mie instan, dan makanan berlemak. Sayur, buah, dan makanan sehat kini lebih banyak mengisi piringnya.
Namun, pengalaman pahit itu menyisakan trauma mendalam bagi sang istri, Ani Suryani. Peristiwa ketika ia mendapati suaminya tergeletak lemah dengan wajah pucat dan tubuh dingin masih terekam jelas di ingatannya. Detik-detik menegangkan itu seolah menjadi mimpi buruk yang sulit dihapus. Ani mengaku, sejak kejadian tersebut, rasa cemas selalu menghantui setiap kali melihat suaminya merasa lelah atau tidak enak badan.
“Saya traumanya pas kejadian, tiba-tiba bapak seperti itu. Kondisinya sudah pucat, dingin, seperti mati. Saking paniknya saya sampai nggak napak. Sebelumnya hampir tiap malam bapak makan mie, makannya memang kacau. Setelah operasi, berat badannya turun, saya bantu ubah pola makan jadi tanpa gorengan, tanpa minyak dulu. Sekarang pelan-pelan mulai sehat lagi,” kisah Ani.
Herlansyah sendiri kini seumur hidupnya bergantung pada obat-obatan pengencer darah dan penurun kolesterol untuk menjaga jantungnya tetap stabil. Meski begitu, ia mengaku bersyukur masih diberi kesempatan kedua.
“Kalau pesan saya jangan sampai ngalamin seperti saya. Tolong jalani pola hidup sehat, dari makanan sampai olahraga. Resikonya sudah saya rasakan sendiri. Alhamdulillah masih diberi umur panjang, dan itu harus saya manfaatkan untuk hidup lebih bijak,” ucapnya penuh harap.
Di sisi lain, Indonesia masih tertinggal dalam upaya eliminasi lemak trans. Saat negara tetangga seperti Singapura dan Thailand telah melarang penggunaannya, Indonesia masih sebatas wacana.
Ahli penyakit jantung intervensi, Dr. Fadjar H. Sahal, SpJP(K), menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah tegas.
“Indonesia belum punya aturan jelas untuk eliminasi. Saya berharap Kemenkes segera melakukan itu. Bisa dengan membatasi kadar lemak trans hanya 2%, atau langsung menghapus seluruhnya dari produksi dan peredaran. Karena kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak?” tegas Fadjar.
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur eliminasi lemak trans industri. Padahal, tercatat sudah ada 53 negara di dunia yang menerapkan kebijakan tersebut sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dari kawasan ASEAN, Singapura dan Thailand telah lebih dulu memiliki regulasi tegas terkait penghapusan lemak trans dari rantai pangan.
Baginya, tanpa pernyataan resmi dan komitmen kuat dari pemerintah, terapi medis hanyalah langkah kecil. Ancaman sesungguhnya ada pada lemahnya regulasi. Pada akhirnya, lemak trans bukan sekadar istilah di balik label makanan. Ia adalah ancaman nyata yang perlahan menggerogoti kesehatan masyarakat. Tanpa aturan yang jelas, jutaan nyawa dipertaruhkan. (**)