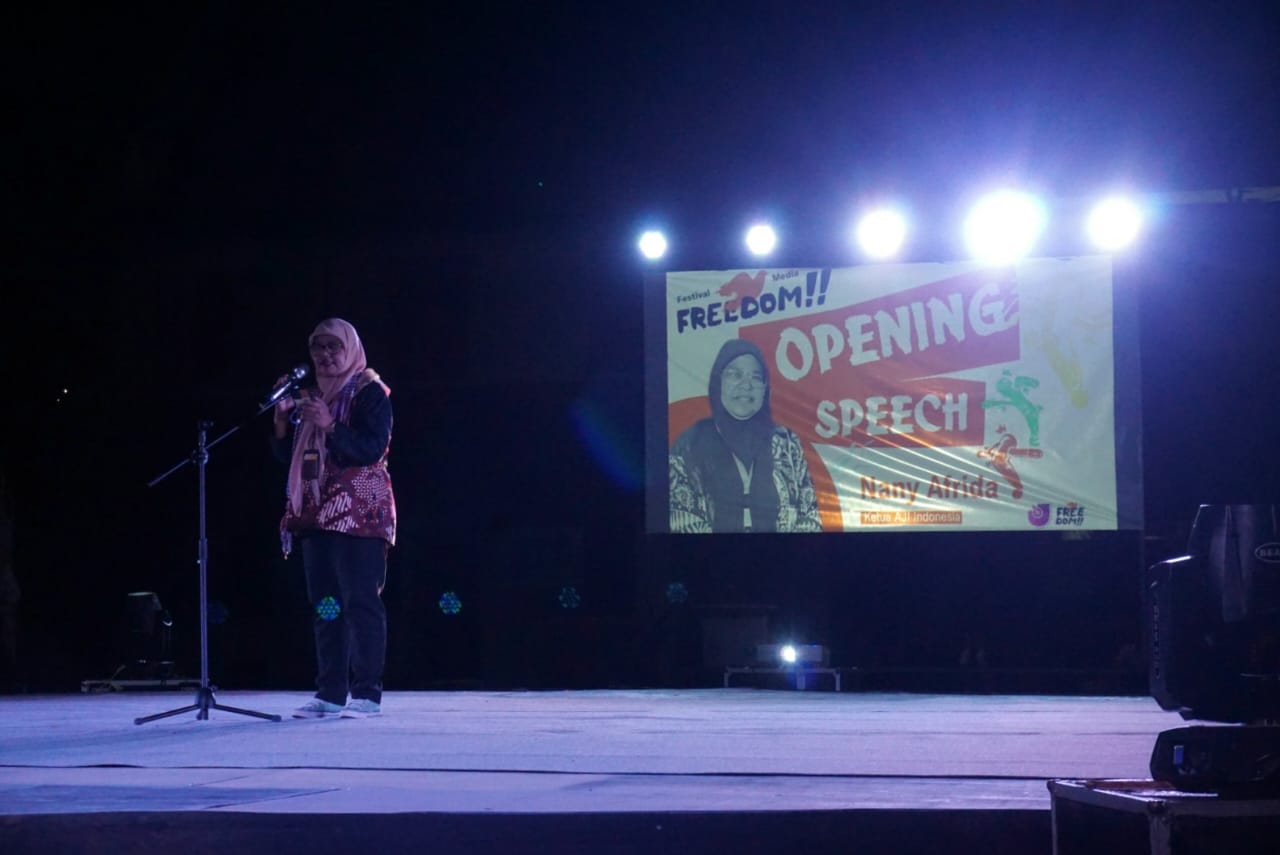Oleh Yulia A
INDEPENDEN -- Ratusan kapal terparkir di dekat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terate, Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Dari yang bagus hingga yang butut. Dari yang harganya ratusan juta hingga puluhan juta. Semua ada di sana, tampak dengan cat warna warni.
Setiap pukul 03.00 WIB dini hari, kapal-kapal itu biasanya sudah dipenuhi para nelayan. Mereka riuh tengah bersiap-bersiap untuk melaut.
Tak perlu berlayar jauh hingga ke Kepulauan Seribu, Jakarta. Sebab, hasil tangkapan di sekitar Teluk Banten pun sudah melimpah. Paling tidak, beberapa jam melaut sudah bisa menjaring setengah kwintal ikanlah.
Para nelayan lalu membawa hasil tangkapannya ke TPI dengan raut sumringah. Hasil penjualannya pun masih bisa ditabung. Apalagi harga solar juga masih bisa dijangkau.

Sayang, itu cerita lama. Mungkin, sekitar 17 tahun lalu. Sebab, masa-masa indah bagi nelayan itu kini sudah berbalik drastis.
"Saya sudah dua bulan enggak nangkep ikan," kata Amad kepada Independen.id.
Alasannya bukan karena Amad malas atau sudah tak kuat lagi melaut di usianya yang sudah lanjut. Usianya memang sudah lebih dari 60 tahun (lansia), tapi tenaganya masih kuat.
Amad bercerita, tangkapan ikan semakin hari semakin payah semenjak ada proyek-proyek di kawasan Terate dan di kampung sebelahnya yaitu Kampung Pangsoran, Bojonegara. Termasuk, Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW).
Kawasan industri ini sudah dibangun sejak 2012. Industri milik raksasa agribisnis Wilmar ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019.
Dalam situs resminya, total luas KITW memakan 912 hektare lahan, terdiri dari lahan seluas 760 hektar dan 152 hektar untuk jalan lintas dan terminal dermaga. Wilmar juga mereklamasi area pesisir menjadi pelabuhan seluas 548 hektare.
Pelabuhan itu digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal yang membawa berbagai komoditas Wilmar seperti minyak sawit, beras, tepung hingga margarin.
Amad mengungkapkan air laut dan ekosistem di bawahnya tidak lagi sama setelah ada KITW. Ikan-ikan lari entah ke mana.
"Semua seluruh nelayan sampai Bojonegara itu sepi, enggak ada ikan. Yang dulu dulu enggak (sepi ikan). Semenjak ada proyek proyek ini aja," ujarnya.
Dahulu, kata Amad, berbagai jenis ikan banyak ditemui di Teluk Banten. Ikan kembung, tengiri, bahar sampai udang melimpah bisa didapatkan dengan mudah.
Sebelum ada KITW, Amad bisa menangkap lebih dari setengah kwintal atau 50 kilogram. Berangkat dari pukul 4 pagi hingga 11 siang. Sekarang, 1 kilogram saja susah.
"Dapet paling 5 biji ekor ikan kembung. Ikan yang lainnya enggak ada. Ikan Bahar udah enggak ada," keluhnya lagi.
Jika dijual, 5 ekor ikan itu hanya bernilai Rp40 ribu. Uang tersebut, untuk dibelikan solar saja tidak cukup. Apalagi harga solar kini mahal dan sulit didapat.
Harga solar saat ini Rp9 ribu per liter. Amad membutuhkan minimal 30 liter untuk bisa menangkap ikan ke tengah Teluk Banten. Artinya, dia harus mengeluarkan uang Rp270 ribu untuk sekali melaut.
Lebih tinggi pasak daripada tiang. Oleh sebab itu, banyak nelayan yang lebih memilih diam di rumah seperti Amad.
"Nelayan tinggal dikit sekarang. Pada bangkrut. Uh dulu mah baris kapal nelayan. Sekarang mah enggak ada tinggal beberapa. Pada bangkrut," ucapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikumpulkan media ini, tangkapan laut mulai mengalami penurunan drastis pada 2019. Pada tahun itu, jumlah tangkapan laut di Kabupaten Serang hanya 7.542 ton. Ini jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pada 2018, hasil tangkapan laut mencapai 16.654 ton.
Jumlah tangkapan ikan sempat naik pada 2019 dan 2020. Nelayan di Kabupaten Serang total mendapat 7.542 ton pada tahun 2019 dan 9.592 ton pada 2020. Namun, kembali mengalami penurunan tahun 2021, hasil tangkapan laut yang didapat nelayan sebanyak 7.782 ton. Kemudian, menurun lagi menjadi 7.213 ton pada 2022.
Tidak ada penjelasan soal ini.
Sore itu, Selasa, 25 Februari 2025, Amad berada di atas kapalnya yang dia beli 27 tahun lalu. Dia hanya membersihkan air hujan yang masuk menggenangi kapalnya.
Meski menjadi nelayan saat ini makin sulit, Amad masih menggantungkan harapannya pada laut. Jika kapalnya dibiarkan terisi air hujan, bisa tenggelam. Tamat riwayatnya.
"Dulu banyak kapal di sini tapi karena engga diurus pada tenggelam," ucap dia.
Reklamasi yang Ditolak Nelayan
Apa yang terjadi dengan Amad dan ratusan nelayan lainnya saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran mereka sejak lama. Pada 2019 silam, para nelayan menolak rencana reklamasi pelabuhan Wilmar.

Mereka takut reklamasi tersebut akan berdampak pada hasil tangkapan laut. Terlebih, pada tahun itu, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan oleh DPRD Provinsi Banten.
Anehnya, berdasarkan pantauan dari citra satelit, pada 2019 sudah terjadi penambahan daratan sekitar 18 hektare di kawasan Wilmar. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menunjukkan luas perairan laut di Kabupaten Serang mengalami penyusutan.
Pada 2009, luas perairan laut di Kabupaten Serang mencapai 814 km2. Namun, pada 2011 menjadi 680,8 km2.
Sebaliknya, luas daratan justru mengalami penambahan.
Pada 2009, luas daratan adalah 1.437,41 km2, kemudian bertambah menjadi 1.467,35 km2 pada 2011.
Padahal, RZWP3K baru disahkan pada 7 Januari 2021. Itu pun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil Banten.
Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan, Agus Pambagio menjelaskan setiap pembangunan harus mengikuti aturan yang ada dengan mekanisme yang jelas. Apalagi, jika berstatus PSN.
Sebelum diputuskan adanya pembangunan di suatu daerah, harus ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Agus menyebut penyusunan AMDAL harus melibatkan akademisi dan masyarakat lokal.
Partisipasi masyarakat penting karena dalam sebuah pembangunan. Alasannya masyarakat setempatlah yang akan terdampak pembangunan tersebut.
"AMDAL harus ada konsultasi publik sama masyarakat. Kalau direklamasi AMDAL belum keluar ya nggak bisa," kata Agus.
Selain AMDAL, Agus menjelaskan pembangunan juga harus mengacu pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut harus berlandasakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/kota.
"Harus mengacu RTRW, baru Perda. Jadi,kalau RTRW-nya belum ada. Ya, nggak boleh. Itu harusnya batal,” kata dia lagi.

Reklamasi yang dilakukan oleh PT Wilmar bukan hanya tidak memiliki RZWP3K, melainkan juga belum ada di Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031.
PSN Kawasan Industri Wilmar baru dimasukan ke dalam RTRW setelah direvisi pada 2020 silam. PSN tersebut tertuang di Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Serang tahun 2011-2031.
Padahal, reklamasinya sudah berlangsung sejak 2019.
Kini, kekhawatiran Amad ratusan nelayan lainnya sudah terjadi. Laut tercemar dan ekosistem di dalamnya rusak hingga menyebabkan hasil tangkapan nelayan turun drastis.
Udin, salah satu nelayan di Kampung Terate juga sudah jarang melaut. Ongkos dan logistik untuk sekali melaut sangat mahal. Jika ingin mendapatkan hasil tangkapan yang lumayan, Udin harus berlayar hingga kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Itu juga dengan modal yang besar.
Setidaknya Udin harus membeli solar minimal 60 liter dan membawa logistik senilai Rp2 juta. Belum lagi, harus siap meninggalkan keluarga selama tiga hari.
"Sebelum ada proyek (PSN,red), nangkap itu gampang. Sekarang itu susah. Susah sekali. Kalau dulu enaklah enggak perlu ke Kepulauan Seribu," kata Udin.
Selama KITW ada, Udin mengaku tidak pernah mendapatkan kompensasi apapun atas dampak kerugian yang berimbas pada nelayan.
"Orang yang ngerti itu mikirin perut sendiri. Nelayan enggak dipikirin," keluhnya.
Padahal, Udin merasakan langsung dampak KITW dan proyek-proyek lainnya di sepanjang Teluk Banten . Sesekali dia bahkan pernah melihat limbah dibuang begitu saja ke laut.
"Kadang-kadang airnya keruh. Panas lagi, mungkin kena limbah. Limbah Wilmar sama PLTU Jawa 7. Ikannya jadi ngejauh. Enggak mungkin kan laut enggak ada ikan. Tapi ngejauh," tuturnya.
"(Limbahnya) Kayak lumut-lumut gitu. Menggumpal. Warnanya coklat," tambahnya.
Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati melihat permasalahan yang timbul saat ini di sekitar teluk Banten berpangkal dari aturan yang tidak memihak apalagi melibatkan masyarakat.
Payung hukumnya, yaitu Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) yang direvisi tanpa melibatkan masyarakat sipil pada 2020 silam misalnya. Ini berimbas pada aturan-aturan turunan seperti RTRW hingga RZWP3K.
Selain tidak partisipatif dalam proses mebuatannya, aturan itu juga lebih mengutamakan mencari keuntungan tanpa memperhatikan aspek lain, seperti keberlanjutan lingkungan. Susan tak heran jika akhirnya peraturan-peraturan itu meugikan masyarakat.
Dia mencontohkan reklamasi.
Di desa-desa pesisir yang terdapat reklamasi, Rerata misalnya, para nelayannya mengeluh kehilangan tangkapan drastis.
"Kalau awal-awal mulai direklamasi itu, dampak yang mereka rasakan awal-awal itu adalah hasil tangkap yang semakin berkurang. Efek dari penimbunan itu akan merubah aris air. Itu sudah pasti," kata Susan.
"Dan itu pasti ikan tidak akan bertahan berada di ekosistem yang rusak seperti itu. Dia pasti akan migrasi ataupun mereka akan pelan-pelan itu hilang," imbuhnya.
Peneliti Ahli Utama Bidang Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Widodo S. Pranowo melakukan analisis kondisi rona lingkungan pesisir perairan Teluk Banten dan hipotesis dampaknya kepada perikanan tangkap tradisional.
Widodo mengungkapkan ada perubahan signifikan di sekitar Teluk Banten pada 1985 dan 2024 atau dalam rentang waktu 40 tahun.
Menurutnya ada beberapa perubahan, di antaranya perubahan tata guna lahan pesisir, adanya perubahan/pergeseran garis pantai sejauh beberapa ratus meter pantai baik yang diakibatkan oleh reklamasi dan bangunan pesisir maupun yang diakibatkan oleh erosi dan sedimentasi, serta indikasi adanya perubahan pulau-pulau kecil.


Widodo menyebut pesisir Teluk Banten pada 1985, masih didominasi oleh lahan pesisir alami dan pertanian. Tidak terlihat adanya infrastruktur besar di sepanjang pesisir teluk. Kondisi air lautnya tampak lebih jernih dengan zona transisi air laut dan darat yang lebih halus.
"Pulau-pulau kecil di tengah teluk juga tampak lebih alami, mengindikasikan sedimentasi belum terjadi," kata Widodo kepada Independen.id.
Sedangkan pesisir Teluk Banten pada 2024, tampak adanya perkembangan industri dan infrastruktur pesisir yang cukup masif, termasuk pelabuhan dan kawasan industri.
Dia menjelaskan struktur reklamasi dan pelabuhan besar dominan terlihat di sebelah barat daya teluk. Kondisi ini mungkin berkontribusi terhadap perubahan hidrodinamika arus dan gelombang di dalam perairan teluk, yang kemudian berpengaruh kepada sebaran partikel sedimen, baik yang berasal dari muara-muara sungai di dalam teluk, maupun yang dari luar teluk.
Berdasarkan citra satelit tahun 1985 dan 2024, Widodo mengatakan ada perubahan signifikan dalam sebaran terumbu karang akibat tekanan lingkungan, sedimentasi, dan pembangunan pesisir. Namun, hal ini perlu dilakukan survei pengecekan langsung (in site observation/ ground truth).
Widodo juga mengungkapkan berdasarkan kondisi habitat yang tersedia di Teluk Baten, maka kemungkinan jenis ikan yang dominan mungkin bukan ikan karang yang bergantung pada terumbu, tetapi lebih ke ikan pelagis.
Hasil tangkapan kemungkinan akan menjadi lebih fluktuatif dibanding dari waktu ke waktu karena perubahan habitat.
"Dampaknya nelayan harus beradaptasi, mungkin dengan cara memperluas area tangkapnya atau menggunakan alat tangkap yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini. Namun, tantangannya dengan memperluas area tangkapnya maka akan meningkatkan jumlah konsumsi bahan bakar minyak (BBM)," jelas dia.
Mereka yang tersingkir
Sulitnya mencari ikan di laut membuat banyak nelayan terpaksa pensiun dini. Tinggal puluhan orang saja yang masih bertahan menjadi nelayan, beberapa di antaranya Amad dan Udin.
Amad mengatakan anak-anak muda di Terate mungkin masih bisa diserap oleh KITW dan industri. Namun, bagi orang-orang dengan seusianya sudah tidak bisa.
Oleh sebab itu, dia masih mencari ikan. Meskipun, intensitasnya berkurang drastis karena lebih sering ruginya.
"Udah tua mah susah ada pabrik juga enggak bisa kerja. Enggak diterima kerja. Yang muda masih enak," kata Amad.
Yeye (bukan nama sebenanrnya), juga mengalami hal serupa. Usianya pada tahun ini menginjak 60 tahun, namun dia sudah memutuskan untuk pensiun sebagai nelayan sejak beberapa tahun lalu.
Yeye mengaku kesulitan untuk melaut semenjak ada proyek. Akses menuju area tangkap ikan, kini dijaga ketat oleh sekuriti.
"Yang di depan pantainya gak ada. Iya, dimarahin sama sekuritinya. Sekarang kita gak bisa masuk sembarangan. Jangankan orang lain. Kelompok warga di sini aja sekarang gak bisa masuk sembarangan. Karena udah ada proyek," kata Yeye.
Dia tak memungkiri bahwa proyek-proyek yang berdiri di Kabupaten Serang, termasuk KITW bisa menyerap warga lokal. Namun, tetap tenaga kerja yang diserap itu masih sedikit jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar Banten.
Yeye mengibaratkan, "Pada akhirnya banyak semut mati di tumpukan gula." Banyak yang tersisih di tempatnya sendiri.
Yeye sedikit beruntung mempunyai tiga anak yang sudah bekerja semua. Dia pun bisa pensiun dini dan mengurus cucunya. Dia tidak membayangkan jika dirinya seperti kebanyakan orang di Kampung Terate yang menggantungkan kehidupannya pada laut.
Data Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Banten menunjukan ada penurunan jumlah nelayan.
Pada 2013, jumlah nelayan mencapai 5.115 orang. Namun, pada 2016 turun menjadi 4.849 orang. Angkanya terus merosot, hingga pada 2021, jumlah nelayan hanya 723 orang.
Direktur Pena Masyarakat Banten Mad Haer menilai nelayan dan warga pesisir menjadi pihak yang paling tersisih di Kabupaten Serang. Dia menduga hal ini terjadi lantaran tidak ada analisis yang matang dan keberpihakan pemerintah saat mengeluarkan izin usaha atau industri.
Secara turun-temurun warga di Kampung Terate dan Pangsoran diajarkan ilmu-ilmu melaut. Sebagian lagi, belajar bagaimana bercocok tanam dan mengairi sawah.
Ketika proyek-proyek masuk, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh warga secara turun-temurun itu kurang relevan dengan industri. Walhasil, tidak banyak yang terserap oleh indutsri di tempat mereka lahir.
"Ada perubahan pola hidup dan pendidikan. Tidak mungkin orang yang dulu suka ngebajak sawah, (disuruh) pencet tombol mesin dan sebagainya, ataupun ngebenerin mesin dan sebagainya," kata pria yang akrab disapa Aeng saat ditemui di sekretariatnya, di Banten, Rabu (26/2/2025).
Dari segi ekologis, PSN yang dikelola oleh raksasi industri agribisnis ini juga bermasalah. Menurut Aeng, perlu adanya pengecekan dan evaluasi dari pemerintah pusat. Pasalnya, dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat.
"Apalagi yang di dekat Wilmar juga ada PLTU kan. Itu malah nambah parah gitu. Belum lagi daerah laut itu kan namanya Teluk Banten ya udah makin rusak. Sebelumnya di situ juga pasirnya kan ditambang,"ucapnya.
Menurut dia pemerintahnya tidak membuat peraturan untuk masyarakat, melainkan hanya untuk investasi.
"Apalagi statusnya ditambah-tambah PSN, kan berarti tambah pengamanan, entah itu polisi, bisa jadi entar tentara, tentara malah lebih-lebih brengseknya adalah tentara khusus langsung yang jaga PSN," imbuhnya.
Terkait dampak kerugian dan dugaan pencemaran lingkungan dari PSN ini, Independen.id telah menghubungi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Suroto untuk meminta tanggapannya.
Dia mengatakan semua tanggapan akan disampaikan lewat Humas Kemeko Perekonomian.
"Mungkin semua permintaan informasi bisa melalui Biro Klip/Humas Kemenko Perekonomian," ujar Suroto.
Namun, Humas Kemenko Perekonomian hingga tulisan ini dibuat belum juga memberikan tanggapannya.
"Saya coba sampaikan ke pimpinan dulu," kata Kuanefi, Biro Humas Keneko Perekonomian.
Independen.id juga telah menghubungi Gubernur Banten Andra Soni, Direktur PT Wilmar Indonesia Erik Tjia dan Public Relations Assistant Manager at PT Wilmar Alina Muta'idah. Namun, ketiganya juga belum merespons hingga saat ini.
==
Liputan ini merupakan bagian dari program Fellowship “Mengawasi Proyek Strategis Nasional” yang didukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia