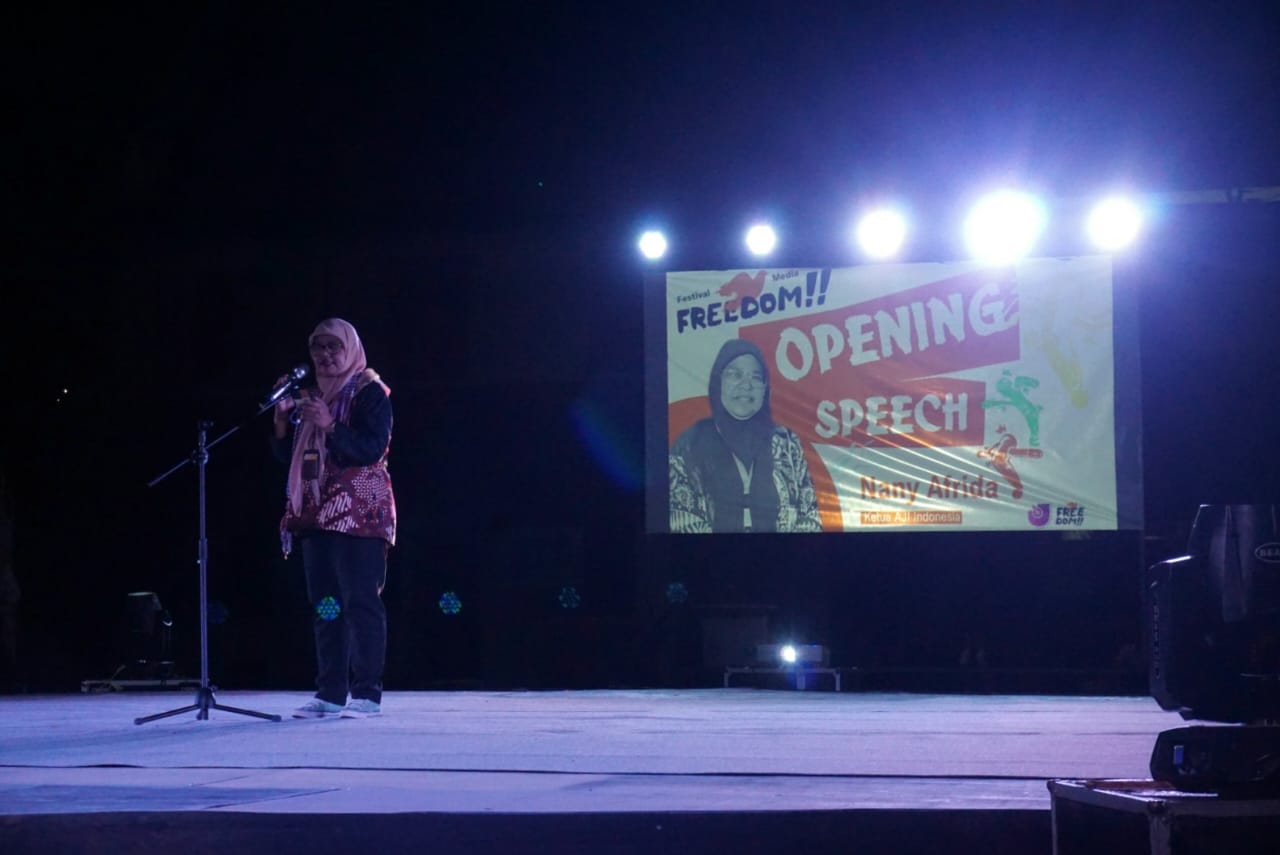Oleh Fadiyah Alaidrus
INDEPENDEN-- Ch* (25) bersiap untuk berangkat kerja. Dia adalah satu dari 18,48 persen pekerja di Jakarta yang harus melakukan perjalanan panjang menuju tempat bekerja. Khusus untuk Ch yang berprofesi sebagai pekerja lepas, dia akan berangkat dari kota satelit, Bintaro, Tangerang Selatan menuju lokasi kerjanya di Blok M, Jakarta Selatan.
Ch bekerja secara serabutan di berbagai bidang, termasuk 1,5 tahun terakhir di bidang pendidikan. Sebelumnya, ia bekerja di industri perfilman, tetapi kondisi kesehatannya membuatnya sulit untuk melanjutkan karirnya di industri tersebut.
Ch merupakan satu dari banyaknya orang dengan disabilitas yang tidak terdata di DKI Jakarta, terlebih dengan posisinya sebagai invisible disability atau disabiltias yang tidak terlihat.
Pagi itu, Jumat awal Desember 2024, Ch mendatangi halte Feeder Transjakarta yang menurutnya, “enggak bisa dibilang halte juga sih, soalnya enggak ada tempat duduk.”
Halte tersebut juga tidak melindungi pengguna fasilitasnya dari sinar matahari. Sementara, Ch memiliki autoimun yang membuat tubuhnya tidak bisa terpapar matahari secara langsung, dan mengalami kesulitan untuk berjalan kaki terlalu jauh.
“Biasanya pembuluh darahnya tuh [kalau] ke-trigger, jadi pecah gitu. Selain karena jalan banyak, bisa karena kena matahari juga,” jelas Ch.
“Aku tuh bener-bener enggak bisa kena matahari. Begitu kena, sinar matahari berasa kayak langsung nembus tulang. Sakit, panas. Kayak ditusuk-tusuk,” lanjutnya.

Sesampainya di Blok M, Ch masih harus keluar dari halte dengan cara menuruni dan menaiki tangga, kemudian meneruskan perjalanannya sekitar 400 meter menuju kantor.
Ini bukan pengalaman yang menyenangkan untuk Ch. Jakarta memang masih jauh dari ramah untuk mereka yang disabilitas seperti Ch.
Saat ini, hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang memiliki data terlengkap tentang orang dengan disabilitas. Data itu menyebutkan 57.881 dari 8.214.007 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta memiliki disabilitas. Sayangnya data tersebut tidak mencerminkan data sebenarnya karena tidak menghitung orang-orang di luar dari DPT, termasuk anak dengan disabilitas.
Dari tujuh narasumber dengan disabilitas yang diwawancarai untuk naskah ini, seluruh narasumber menyampaikan bahwa transportasi publik di DKI Jakarta masih sulit untuk diakses oleh mereka. Mirisnya lagi, dua dari tujuh narasumber memilih untuk tidak menggunakan transportasi publik sama sekali.
“Aku ngerasa kayaknya banyak sekali transportasi umum tuh bukan dibuat untuk aku sebagai disabilitas,” ujar Laninka (33), perempuan penyandang disabilitas daksa sekaligus seorang pekerja lepas yang memilih untuk tidak menggunakan transportasi publik di DKI Jakarta.
Terakhir kali Laninka menggunakan transportasi umum adalah pada 2018 silam. Itu adalah pengalaman terburuknya. Saat itu, ia kesulitan untuk menaiki halte Transjakarta karena jalurnya yang terlalu curam, serta harus ikut berjalan di tengah kemacatan jalan dan terpapar asap dari knalpot motor karena trotoar justru dipenuhi oleh pedagang kaki lima.
Sebagai orang dengan disabilitas yang rutin menggunakan transportasi publik, Ch selalu mengakhiri harinya dengan badan yang sakit dan remuk.
Hari itu Ch pulang menggunakan motor, diantar oleh pasangannya. Keesokan harinya, Ch mengalami sakit kepala, radang tulang, demam, dan sulit untuk menggerakan sendi-sendinya.
“Aku kalau habis commuting keluar tuh harus istirahat ya sehari. Keesokan harinya, badanku pasti ambruk,” ujar Ch.

Peluang Perbaiki Fasilitas Publik
Sulitnya masyarakat dengan disabilitas untuk mengakses transportasi publik bertentangan dengan ambisi pemerintah untuk mulai mererapkan transisi energi atau transisi dari penggunaan energi kotor ke energi yang lebih bersih.
Dengan kontribusi emisi gas rumah kaca yang tinggi (28%), transportasi menjadi fokus dalam program transisi energi. Pemerintah DKI Jakarta menargerkan pengguna transportasi publik meningkat dari 18 persen menjadi 60 persen pada 2030.
Namun bagan gambaran besar perencanaan yang dipublikasikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memang tidak menyebut soal akses pemenuhan untuk orang dengan disabilitas maupun pembangunan fasilitas yang inklusif.
Tidak ada dokumen yang membahas soal perencanaan ataupun implementasi transisi energi di transportasi publik yang memastikan akses bagi masyarakat dengan disabilitas.
Dokumen MRT Jakarta yang membahas soal rencana dan implementasi transisi energinya hanya satu kali menyinggung kata disabilitasi. Begitu pun dengan laman resmi Transjakarta yang membahas soal program sustainability atau keberlanjutannya.
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KRL cukup banyak menyinggung soal disabilitas dalam dokumennya, tetapi mayoritas membahas soal penghargaan dan fasilitas ramah disabilitas yang mereka miliki. Namun seluruh narasumber dengan disabiltas justru menilai bahwa KCI merupakan pilihan transportasi yang paling sulit untuk mereka akses.
Ch mengaku menghindari menggunakan KCI karena sulit untuk mendapatkan tempat duduk di pagi hari. Ch juga jarang mendapatkan kursi prioritas karena disabilitasnya yang tidak terlihat. Kondisi diperparah dengan kondisi stasiun yang sulit diakses. Stasiun paling dekat dengan rumahnya adalah Pondok Ranji, dan Ch harus menggunakan banyak tangga untuk menyebrang dari satu sisi peron ke sisi lainnya.
Ch sebetulnya bisa menghampiri petugas untuk menjelaskan kondisinya. Namun ia lebih sering menghindarinya karena akan memakan waktu yang lebih banyak.
Qurrata A’yuna (28), akrab dipanggil Yuna, perempuan dengan disabilitas daksa, juga memilih untuk menghabiskan waktu 2,5 jam menggunakan Transjakarta dari Depok menuju ke kantornya di Jakarta Pusat. Sekalipun, perjalanan menggunakan KCI hanya memakan waktu sekitar satu jam.
“Celah dari peronnya terlalu tinggi menurut aku. Aku agak susah kalau harus sendiri. Terus aku kan keluar tuh kemana-mana juga sendiri kan,” jelas Yuna yang sehari-harinya bekerja sebagai frontend engineer.
Menurut Eka Permanasari, lektor kepala desain perkotaan Monash University Indonesia, upaya untuk melakukan transisi energi masih lebih banyak dilakukan dalam lingkup armadanya, seperti pergantian transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, Transjakarta mengganti busnya menjadi bus listrik.
Namun upaya untuk mengganti atau mengubah fasilitas publik tersebut tidak diiringi dengan memastikan aksesnya terhadap masyarakat dengan disabilitas. Sementara, menurut Eka, idealnya upaya untuk transisi energi turut dijadikan kesempatan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas.
“Secara otomatis, maka desain bus [yang sudah menggunakan tenaga listrik] harus bisa mengakomodir kebutuhan [disabilitas], kayak seharusnya sudah tidak ada celah antara halte dan bus,” ujar Eka saat dihubungi pada 21 Desember 2024.
Selain itu, ujar Eka, upaya untuk membangun transportasi publik yang inklusif tidak berhenti pada transportasi publiknya, melainkan tata kota dan jalur untuk mengakses transportasinya.
“Jadi kalau ngomongin komprehensif, enggak bisa ngomongin armadanya saja, [tapi perjalanan] ke sananya susah. Percuma punya armada yang ramah disabilitas, tapi orang disabilitasnya enggak bisa ke sana,” tegas Eka.

Menurut Rina Prasarai, Ketua dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), langkah untuk memastikan agar upaya transisi energi di transportasi publik menjadi inklusif adalah dengan melibatkan organisasi atau masyarakat dengan disabilitas dalam prosesnya.
Alasannya, ungkap Rina, “Yang tahu dan paham rasanya jadi disabilitas ya cuman penyandang disabilitas.”
Namun, ujar Rina, sejauh ini, pelibatan organisasi atau masyarakat dengan disabilitas hanya dilakukan sebatas mengundang masyarakat dengan disabilitas untuk mencoba transportasi yang sudah jadi. Kemudian mereka diminta untuk memberikan masukan atau umpan balik.
“Banyak pembangunan itu manggil kita, tapi enggak di seluruh proses padahal yang harusnya terjadi adalah mereka dari mulai merencanakan itu, ajak kita sehingga enggak sia-sia nanti,” ujar Rina, perempuan dengan disabilitas sensorik netra, saat ditemui pada 7 Desember 2024.
“Ini kadang-kadang udah mau selesai, baru kita diundang. Terus pas kita mau protes, udah kadung [dibangun transportasinya],” lanjutnya.

Harga yang Harus Dibayar
Dengan tidak adanya pelibatan orang dengan disabilitas, ujar Rina, akhirnya transportasi publik ramah lingkungan yang terbangun pun tidak bisa diakses oleh mayoritas masyarakat dengan disabilitas.
“Kita juga ingin menjadi bagian dari masyarakat yang menurunkan tingkat emisi di negara ini, tetapi kita mau keluar rumah saja susah,” kata Rina.
“Akhirnya kita lebih memilih untuk menggunakan taksi, yang ibaratnya energinya hanya kita gunakan untuk sendiri saja, atau dengan pendamping, tapi kan kalau menggunakan transportasi publik itu, satu energi dibagi dengan banyak orang,” lanjutnya.
Rina menegaskan bahwa seharusnya masyarakat dengan disabilitas berhak untuk berkontribusi dalam menekan angka emisi dan menggunakan transportasi publik. Terlebih, mereka juga berkontribusi melalui pembayaran pajak ke negara.
“Dan itu kan (pakai) duit gue juga. Kan kita bayar pajak,” tegasnya.
Rina menjelaskan bahwa ada beberapa langkah penting untuk melakukan pelibatan yang lebih menyeluruh terhadap masyarakat dengan disabilitas. Pertama, pelibatan dilakukan saat masih tahap perencanaan, termasuk perencanaan proyek dan biaya.
“Jadi kalau dari awal sudah dihitung, itu harusnya enggak akan ada cost tambahan lagi,” ujar Rina.
Kedua, dalam tahap pembuatan desain fasilitas dan transportasi publik yang ramah lingkungan, pemerintah dan penyedia layanan harus melibatkan orang-orang dengan bentuk disabilitas yang beragam sehingga fasilitas yang nantinya terbentuk bisa digunakan oleh semua orang, serta tidak ada yang tertinggal.
Terakhir, saat fasilitasnya sudah terbentuk, maka pemerintah dan penyedia transportasi publik harus memperkerjakan orang-orang dengan disabilitas sebagai pakar. Tujuannya, untuk memastikan agar transportasi publik selalu inklusif, bukan hanya dalam proses pembangunannya.
“Lebih jauh lagi, mereka bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan transisi energi ini, yang akhirnya bisa membuka peluang baru untuk penyandang disabilitas agar bisa bekerja di sektor transisi energi,” pungkas Rina.
Menurut Ilma Rivai (28), pegiat isu disabilitas dan gender, sebetulnya transportasi publik yang ramah disabilitas tak sebatas menguntungkan orang-orang dengan disabilitas.
“Jadi ini tuh bukan cuman untuk kalangan tertentu saja, bukan hanya untuk disabilitas. Misalkan, kalau kita bikin fasilitas lebih aksesibel gitu, selain orang dengan disabilitas, ibu hamil atau membawa anak juga lebih mudah gitu, atau kalau bawa stroller juga jadi lebih mudah,” ujar perempuan yang juga menggunakan kursi roda dan memilih untuk tidak mengakses transportasi publik.
Selain itu, ujar Ilma, pada dasarnya semua orang pun bisa mengalami disabilitas, baik yang temporer maupun permanen, seperti akibat kecelakaan atau seorang lansia yang sulit untuk berjalan terlalu lama.
Pihak Transjakarta, MRT Jakarta, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak membalas pesan untuk mengkonfirmasikan permasalah ini. Sementara, pihak KCI menilai bahwa transportasinya sudah ramah untuk disabilitas.
“Sebenarnya kita sudah berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kita [...] yang mungkin tentu upaya ini belum bisa memuaskan semua kepentingan,” ujar Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, saat dihubungi pada 13 Desember 2024.
“Jadi sekali lagi, kita berterima kasih atas masukan-masukan ini. Jika dirasa masih kurang, mungkin nanti ke depan, kami akan tingkatkan lagi upaya-upaya kepada difabel tersebut,” lanjutnya.
Terkait dengan permasalahan jalur untuk transit dari satu transportasi ke transportasi publik lainnya, Aldian Ramadhan selaku Corporate Communication Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) menyampaikan bahwa MITJ akan terus memastikan untuk upaya integrasi transportasi yang lebih ramah disabilitas.
“Lebih masif lagi, tentu harus ada kolaboasi antar public transport operator dan regulator [pemerintah], kerja sama antar stakeholder dan MITJ sebagai eksekutor integrasinya,” ujar Aldian pada 13 Desember 2024.
*Ch merupakan nama panggilan dan bukan nama lengkap. Ch memilih untuk tidak menggunakan identitas lengkapnya untuk tulisan ini.
===
Liputan ini merupakan bagian dari program Fellowship “Journalist Fellowship and Mentorship Program for Just Energy Transition” yang diselenggarakan Remotivi dan WRI.