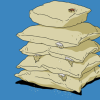Oleh: Ais Fahira
INDEPENDEN- Konflik agraria merupakan sengketa kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah antara masyarakat dengan pihak lain—baik negara, perusahaan, maupun individu—yang kerap berujung pada perampasan ruang hidup. Di Indonesia, konflik agraria bukan sekadar perebutan lahan. Karena tanah menjadi sumber penghidupan utama, terutama bagi petani, masyarakat adat, dan komunitas di pedesaan. Karena itu, setiap benturan kepentingan atas lahan selalu meninggalkan jejak penderitaan sosial yang panjang.
Pada awal 2024, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) merilis laporan yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling rawan konflik agraria di Asia. Dari enam negara yang disurvei—India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal—Indonesia menempati posisi teratas dengan 241 kasus konflik agraria sepanjang 2023, yang mencakup 638.188 hektare tanah pertanian dan wilayah adat. Angka ini menunjukkan betapa peliknya persoalan agraria yang belum terselesaikan.
Sayangnya, kondisi tersebut tidak membaik pada tahun 2024. Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2024, KPA mencatat kenaikan 21 persen jumlah konflik agraria dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, ada lebih dari 50 kasus tambahan, dengan total 295 konflik yang tersebar di seluruh Indonesia. Konflik-konflik ini melibatkan 1.113.577,44 hektare lahan dan berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa peningkatan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kebijakan pembangunan yang semakin eksploitatif terhadap tanah rakyat. “Wilayah konflik agraria itu berdampak kepada 1,1 juta hektare tanah yang tumpang tindih atau bersumber dari proses pengadaan tanah yang merampas tanah masyarakat, baik berupa wilayah adat, tanah pertanian, maupun permukiman,” ujar Dewi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Siapa yang Paling Terdampak?
Dari puluhan ribu korban, tiga kelompok paling rentan kembali menjadi yang paling terdampak: petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin kota. Mereka kerap berada di garis depan perlawanan terhadap proyek-proyek besar, baik perkebunan, tambang, maupun infrastruktur—yang masuk ke wilayah mereka tanpa partisipasi yang layak.
Petani menjadi kelompok terbesar yang kehilangan tanah garapan akibat perluasan perkebunan sawit, tebu, hingga teh. Masyarakat adat kehilangan hutan adat dan ruang hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Sedangkan masyarakat miskin kota banyak terdampak oleh proyek infrastruktur dan properti yang menggusur pemukiman mereka atas nama pembangunan.
Sektor perkebunan masih menjadi penyumbang konflik terbanyak, yakni 111 kasus. Sekitar 75 persen diantaranya terkait dengan perkebunan kelapa sawit, yang hingga kini masih menjadi sumber sengketa utama antara perusahaan dan warga. Selain sawit, konflik juga muncul di perkebunan tebu, teh, karet, cengkeh, dan hortikultura, yang sebagian besar terhubung dengan rantai industri pangan dan bioenergi.
Masalahnya tidak hanya terletak pada izin usaha, tetapi juga pola penguasaan lahan yang timpang dan minimnya pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Di banyak daerah, tanah rakyat diambil alih melalui skema HGU (Hak Guna Usaha) yang tumpang tindih, tanpa proses ganti rugi yang adil.
Proyek Strategis Nasional dan Pertambangan: Konflik yang Menguat
Selain perkebunan, Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi penyebab 36 konflik baru sepanjang 2024. Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti jalan tol, bendungan, kawasan industri, hingga proyek pariwisata kerap menimbulkan penggusuran dan kehilangan tanah bagi masyarakat sekitar.
KPA mencatat sektor infrastruktur secara keseluruhan menyumbang 79 kasus konflik, mencakup lahan seluas 290.785 hektare dan berdampak pada 20.274 keluarga.
Sementara di sektor pertambangan, terdapat 41 kasus konflik yang melibatkan 71.101 hektare lahan dan 11.153 keluarga. Peningkatan tajam ini, menurut Dewi Kartika, terjadi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
UU tersebut dinilai memperkuat dominasi korporasi tambang dengan mempermudah perpanjangan izin usaha dan melemahkan posisi masyarakat terdampak. “Pasca UU Minerba Perubahan, konflik agraria di sektor tambang naik tajam,” ujar Dewi.
Sektor Kehutanan dan Properti: Sengketa yang Tak Pernah Usai
Selain dua sektor utama di atas, KPA juga mencatat 25 kasus konflik di sektor kehutanan dan jumlah yang sama di sektor properti.
Namun, dampaknya berbeda jauh. Sengketa di sektor kehutanan mencakup area yang jauh lebih luas, yakni 379.588 hektare, dan mempengaruhi 7.056 keluarga. Sebaliknya, konflik di sektor properti hanya mencakup 92 hektare, tetapi tetap mempengaruhi 941 keluarga—umumnya akibat penggusuran di kawasan perkotaan dan wisata.
KPA juga menyoroti munculnya konflik baru di sektor agribisnis seperti food estate serta proyek fasilitas militer. Keduanya disebut menambah kompleksitas konflik karena melibatkan kebijakan negara dan korporasi besar yang sulit digugat oleh masyarakat kecil.
Akar Masalah: Ketimpangan Struktur Agraria
Peningkatan konflik agraria setiap tahun memperlihatkan bahwa reformasi agraria sejati masih jauh dari kenyataan. Tanah yang seharusnya menjadi sumber hidup rakyat justru menjadi komoditas ekonomi dan politik.
KPA menilai akar dari konflik agraria adalah ketimpangan struktur penguasaan lahan, di mana sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh segelintir korporasi besar. Dalam situasi ini, masyarakat adat, petani, dan kelompok miskin kota kehilangan ruang hidup dan akses terhadap sumber daya alam.
Program reforma agraria yang dijanjikan pemerintah kerap berhenti di tataran retorika, tanpa penyelesaian struktural terhadap sengketa yang sudah ada. Alih-alih redistribusi tanah, kebijakan yang dijalankan justru memfasilitasi investasi skala besar yang memperparah ketimpangan.
Jalan Panjang Pembaruan Agraria
Konflik agraria yang terus meningkat seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah.KPA menyerukan agar pemerintah baru mengambil langkah konkret dengan meninjau ulang izin-izin bermasalah, menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah, dan memperkuat pelaksanaan reforma agraria sejati yang berkeadilan sosial dan ekologis.